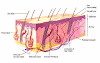Mengapa masyarakat masih menyangsikan kemampuan perempuan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi tubuhnya? Berikut ulasan Uly Siregar. Tulisan ini dipublikasikan di dw.com ditayangkan 7 Maret 2016
Fia namanya. Cantik; dikaruniai kulit terang, mata bulat, bibir merah, dan dada bernas. Janda berumur 39 tahun ini sedang marah. Ia muak jadi korban pelecehan laki-laki saat berjalan kaki di kawasan perkantoran Semanggi. Siulan dan celotehan kotor laki-laki iseng di jalan selalu mengiringi langkahnya. Lebih parah lagi, kadang pria bermotor pun berhenti hanya untuk mencoba peruntungan dan berkomentar, “Sini, Cantik, bonceng yuk sambil peluk.”
Saat mengeluhkan insiden itu di dinding Facebook, reaksi yang muncul makin membuat ia kesal. “Anggap saja itu semacam pujian. Artinya kamu cantik.” Begitu kira-kira komentar yang masuk. Ada juga tuduhan: “Mungkin baju kamu kelewat seksi?” Yang ini membuat Fia berang. Meski tak sampai berjilbab, ia merasa selalu santun dalam berbusana.
Menjadi perempuan memang tak gampang. Tubuh perempuan dianggap sebagai sumber godaan dan dosa hingga menimbulkan masalah—bukan bagi pemilik tubuh, tapi bagi mereka yang melihat. Untuk Fia, tekanan tak hanya muncul dari laki-laki tapi juga kaumnya sendiri, kaum perempuan.
Rekan-rekan sekantornya secara agresif “mengingatkan” agar Fia segera berjilbab. “MasyaAllah, cantiknya wajahmu... Coba ditutup jilbab, pasti makin cantik. InsyaAllah bercahaya.” Sebuah ajakan yang berangkat dari keinginan baik, namun menciderai otoritas si pemilik tubuh. Ajakan berjilbab berubah menjadi teror ketika dilontarkan setiap hari dan membuat perempuan menjadi tak nyaman dengan dirinya sendiri.
Tokoh feminis Simone De Beauvoir mengatakan ketika seorang perempuan memasuki masa puber, tubuhnya pun menjadi sumber rasa takut dan malu. Tak hanya darah menstruasi, bahkan rambut yang tumbuh di bawah ketiak pun menimbulkan perasaan-perasaan negatif. Melewati masa puber, ketidaknyamanan itu berlanjut ke inisiasi seks, pernikahan, hingga menjadi ibu.
Yang lebih menyedihkan, selain menghadapi perasaan-perasaan negatif akan tubuhnya, perempuan pun harus rela tubuhnya diatur oleh pihak lain. Tubuh perempuan diregulasi agar dunia menjadi lebih nyaman bagi kaum Adam. Mereka harus menutup tubuh rapat-rapat agar tak memicu kebrutalan pria.
Bila ada kasus perkosaan di media massa, informasi tak relevan seperti pakaian apa yang digunakan sang perempuan saat diperkosa, atau seberapa cantik wajah dan tubuh korban pun ikut diberitakan. Bila ternyata ada faktor tersebut, korban pun turut dipersalahkan. “Pantas saja diperkosa, roknya kependekan, sih.” Para ibu terbiasa menasihati anak putrinya agar pandai menjaga diri, namun lalai mengajarkan anak laki-laki untuk mengontrol nafsu dan menghargai tubuh perempuan.
Di Aceh, seperti dikutip kantor berita Antara, perempuan dijaring dalam razia pakaian ketat. Nama-nama dan alamat mereka dicatat dalam buku besar. Bila empat kali terjaring maka pelaku dan orang tua akan dipanggil ke kantor Wilayatul Hisbah (polisi syariat). Untuk penjaringan pertama, mereka hanya dinasihati oleh polisi syariat agar tak lagi berpakaian ketat. Tak peduli mereka yang dirazia adalah perempuan-perempuan pengendara motor yang merasa lebih nyaman mengenakan celana jins.
Tubuh perempuan adalah sumber kontroversi. Menjadi perempuan berarti akrab dengan kebingungan-kebingungan yang melelahkan. Ketika perempuan tak menutup rapat tubuhnya, ia dianggap murahan dan wajar bila menjadi sasaran pelecehan seksual.
Pengusung kampanye jilbab di Indonesia bahkan sampai hati menyamakan tubuh perempuan dengan permen: yang dibungkus lebih higienis daripada yang tidak dibungkus. Perempuan berjilbab lebih berharga daripada yang tidak berjilbab. Padahal pada saat yang sama di dunia barat perempuan berjilbab pun dihakimi. Mereka lekat dengan stereotip primitif, terbelenggu, dan berada di bawah kontrol laki-laki. Pilihan perempuan untuk menutupi tubuh dipertanyakan dan diolok-olok.
Lantas bagaimana seharusnya perempuan bersikap? Idealnya, masyarakat menyerahkan otoritas tubuh sepenuhnya kepada pemilik tubuh. Bila perempuan ingin menutupi tubuhnya bergiranglah karena ia meyakininya, bukan karena desakan seorang ibu yang sambil berlinangan air mata memohon pada anak puterinya, “Nak, pakailah jilbab. Ibu merasa sebagai ibu paling merana se-Indonesia karena tak satupun anak ibu yang berjilbab. Ibu malu karena setiap pengajian sering diingatkan ibu-ibu yang lain.” Bila perempuan ingin memakai celana pendek dan baju tak berlengan, ia tak seharusnya menjadi korban pelecehan seksual di jalan.
Sayangnya, untuk hal mendasar seperti memutuskan apa yang layak dikenakan perempuan, masyarakat masih harus turut campur dan menyangsikan bahwa perempuan mampu memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, bagi tubuhnya sendiri.
Penulis:
Uly Siregar bekerja sebagai wartawan media cetak dan televisi sebelum pindah ke Arizona, Amerika Serikat. Sampai sekarang ia masih aktif menulis, dan tulisan-tulisannya dipublikasikan di berbagai media massa Indonesia.
Sumber: dw.com