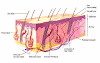[Historiana] - Oleh Alam Wangsa Ungkara. Membicarakan Dipati Ukur tidak kalah menarik seperti halnya membicarakan kisah Perang Bubat. Mengangkat sejarah Dipati Ukur bukan berarti membuka luka lama apalagi mengorek sentimentalisme dangkal kesukuan. Namun sebagai salah satu agar bisa memahami sejarah yang terjadi di masa lalu. Desertasi Edi S Ekadjati (1979), Cerita Dipati Ukur Karya Sastra Sejarah Sunda, menyebut lebih dari 20 naskah yang menyinggung Dipati Ukur yang kemudian dibaginya dalam delapan tipologi: versi Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung, Talaga, Banten, Mataram, dan Batavia.
Ada beberapa versi yang menceritakan kisah Dipati Ukur seperti yang disebutkan diatas. Ada yang menganggap Dipati Ukur sebagai seorang pemberontak dan sebaliknya ada yang menganggap Dipati Ukur sebagai seorang pahlawan. Itu diserahkan kembali kepada masing-masing melihat sejarahnya dari sudut pandang yang mana.
Wangsanata adalah putra Pangeran Adipati Cahyana yang berasal dari Jambu Karang yang kini terletak di wilayah Banyumas. Ia terpaksa menyingkir ke wilayah Priangan karena daerah leluhurnya itu dikuasai oleh Panembahan Senopati dan hegemoninya itu terus berlanjut hingga diteruskan oleh para keturunannya. Setidaknya begitulah yang dituliskan Naskah Sunda Mangle Arum terkait asal usul Wangsanata, yang kelak dikenal sebagai Dipati Ukur.
Bagi masyarakat Banyumas, Pangeran Jambu Karang merupakan leluhur yang menjadi asal-usul berdirinya daerah baru yakni Perdikan Cahyana Purbalingga Banyumas. Dalam cerita rakyat setempat diceritakan, Pangeran Jambu Karang merupakan tokoh dari Sunda yang masih beragama Budha.
Tempat tinggal Wangsanata di wilayah Pasundan adalah Tatar Ukur, wilayah yang dikuasai oleh Adipati Ukur Agung. Tampaknya daerah ini adalah kerajaan yang tidak terlalu besar karena gaungnya tidak sekeras kerajaan-kerajaan Sunda lain. Sebut saja Kerajaan Galuh, Kerajaan Pakuan, dan bahkan Kerajaan Sumedang Larang. Namun demikian, Tatar Ukur menjelma menjadi masyhur karena keberanian pemimpinnya dalam menentang sikap keras Sultan Agung Mataram.
Di Ukur, Wangsanata berkembang menjadi pemuda yang giat, tekun, dan lincah. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu tidak hanya menarik perhatian Adipati Ukur Agung, namun juga menarik cinta putri sang adipati. Tidak ingin kehilangan kesempatan, penguasa Tatar Ukur itupun segera menikahkan putrinya dengan Wangsanata. Semenjak itu, posisi Wangsanata di kerajaan Ukur semakin kuat. Ketika mertuanya tutup usia, Wangsanata naik tahta menggantikannya. Dengan posisinya itu, Wangsanata pun dikenal sebagai Dipati Ukur, penguasa Tatar Ukur.
Menurut Profesor Soegeng Priyadi dalam "Perdikan Cahyana" tidak ada sosok nama Wangsanata di Perdikan Cahyana. Cahyana adalah sebuah perdikan Buddha. Setelah di-Islam-kan Mataram, Cahyana menjadi perdikan bercorak Islam. Semasa kepemimpinan Makdum Kusen, Perdikan Cahyana masih dalam wilayah Pajajaran. Selanjutnya Perdikan Cahyana terlepas dari kekuasaan Sunda Pajajaran (maksudnya Kerajaan Galuh). Sepeninggal Mahdum Cahyana, perdikan Cahyana terbagi-bagi menjadi beberapa daerah perdikan di Kabupaten Purbalingga. Dari babad tersebut Wangsanata tidak disebut-sebut. Dalam Sadjarah Bandung disebutkan bahwa Wangsanata dibawa ke Tatar Ukur oleh Mataram.
Sumber lain mengatakan bahwa Diapti Ukur berasal dari Kerajaan Timbanganten. Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun-temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Ukur Agung, dan Dipati Ukur. Dalam Mangle Arum yang ditulis oleh Nina Herlina Lubis bahwa Adipati Ukur Agung adalah kepala daerah Ukur pertama yang mengakui kekuasaan Mataram atas daerahnya. Ia adalah kepala daerah Ukur yang terlebih dahulu menganut agama Islam. Dalam Naskah Sadjarah Bandung disebutkan bahwa Kerajaan Timbanganten beribu kota di Tegalluar (terletak di lereng Gunung Malabar, dahulu perbatasan antara Distrik Banjaran dan Distrik Cipeujeuh). Diperkirakan Tatar Ukur masuk dalam wilayah Kerajaan Timbanganten yang saat itu berada di wilayah Tarogong Kabupaten Garut.
Dalam artikel jurnal yang berjudul “Dipati Ukur dan Jejak Peninggalannya di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (1627-1633)”, Lasmiyati menungkapkan bahwa Ukur memiliki wilayah yang sangat luas dan mencakup beberapa bagian wilayah sejumlah kabupaten di Jawa Barat saat ini. Menurutnya, wilayah yang ada dalam kekuasaan Dipati Ukur meliputi Sumedang Larang, Karawang, Pamanukan, Ciasem, Indramayu, Sumedang, Sukapura, Limbangan dan Timbanganten.
Pada tahun 1628, perang akan segera bergejolak. Dipati Ukur adalah seorang wedana yang telah memimpin sebuah pasukan besar untuk menyerang Belanda di Batavia atas perintah Mataram.Kenapa perintah pengerahan pasukan Sunda tidak dipercayakan kepada Sumedang Larang?
Saat itu Dipati Sumedang Larang adalah Rangga Gede. Ketika Pangeran Dipati Rangga Gede menerima sanksi politis dari Sultan Agung dan ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni. Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia.
Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Agung adalah menyerang Banten. Akan tetapi untuk menyerang Banten telah terhalang oleh keberadaan VOC di Batavia yang sedang membuat benteng pertahanan. Untuk itu Sultan Mataram menghendaki Dipati Ukur yang telah diangkat oleh Sultan Mataram sebagai bupati wedana di Priangan sanggup membantu Sultan Mataram untuk mengusir VOC di Batavia.
Dipati Ukur (yang menjadi komandan pasukan Pasundan) bersepakat dengan Tumenggung Bahurekso (yang menjadi komandan pasukan Jawa Mataram) untuk bertemu di Karawang, namun pertemuan itu tidak pernah terjadi sehingga keduanya melakukan penyerangan ke Batavia dalam waktu yang berlainan. Penyerangan yang tidak efektif itu tentunya mudah dipatahkan oleh tentara-tentara Kompeni yang memiliki persenjataan lebih maju. Oleh sebab itu, baik pasukan Ukur maupun Bahurekso, gagal dalam penyerangan tersebut.
Menyadari bahwa hasil perang itu tidak akan menggembirakan Sultan Agung, Dipati Ukur hanya memiliki dua pilihan: mati dieksekusi atau mati membela diri. Ia pun memilih opsi yang kedua, karena harga diri serta kehormatan sebagai taruhannya. Ukur berkeliling ke sejumlah tempat di Tatar Sunda, mengajak saudara Pasundannya untuk bersatu dan menentang hegemoni Mataram. Sejumlah lembur, umbul dan dayeuh yang dekat bersedia menerima ajakannya, sedangkan yang lain memilih bersikap pasif dan bahkan ada yang cenderung ingin berkonfrontasi dengannya.
Ketika pasukan Mataram di bawah kepemimpinan Bahurekso dan Narapaksa yang ditugaskan untuk menghukum Dipati Ukur itu berdatangan ke wilayah Pasundan, pasukan Ukur melakukan gerilya dengan komando yang berada di sekitar Gunung Lumbung. Penguasaan mereka atas lapangan, sebetulnya membuat pasukan Dipati Ukur sempat unggul, namun malang tidak dapat ditolak dan untung tidak dapat diraih, sejumlah kepala umbul (kepala lokal) Pasundan yang tidak suka dengan Ukur malah bekerjasama dengan Mataram dan membantu memetakan wilayah pasukan Ukur sehingga kemudian berhasil mematahkan berbagai strategi gerilya yang digunakannya.
Buku ‘Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indië, 1914’ yang ditulis oleh N.J. Krom menyatakan bahwa pada tahun 1833 seorang zoolog dan ahli botani berkebangsaan Jerman, anggota en:Natuurkundige Commissie voor Nederlands-Indië (Komisi Pendidikan Fisika Hindia Belanda) yang bernama Salomon Müller datang ke Gunung Lumbung. Bersama dengan Pieter Van Oort, ia mendapatkan cerita dari sesepuh disana tentang sosok Dipati Ukur hingga tempat peninggalannya. Menurut orang tua tersebut, Gunung Lumbuh adalah pertahanan terakhir Dipati Ukur.
Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara Pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan. Secara teoritis, bila daerah tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah. Setelah “pemberontakan” Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya.
Dipati Ukur harus berhadapan langsung dengan Mataram sendiri yang telah terprovokasi Tumenggung Bahureksa atau Narapaksa. Justru perang melawan Mataram inilah yang menjadi pusaran konflik yang telah menyita tenaga dan pikirannya. Bahkan, pimpinan manusia Sunda lain, yakni Wirawangsa, Samahita Astramanggala, Uyang, dan Sarana, yang diajak angkat senjata, menikam dari belakang dan melaporkan niat pemberontakan Dipati Ukur kepada sultan Mataram.
Setelah terdesak dan berhasil ditangkap, Dipati Ukur dibawa ke Mataram dan menemui ajalnya. Terkait akhir sang penguasa Tatar Ukur tersebut, ada banyak versi eksekusi dan tokoh yang berjasa dalam mematahkan perlawanannya. Namun yang jelas, sang dipati dihukum mati dan tokoh yang membawanya ke Mataram adalah orang-orang Sunda sendiri. Menurut Karel Frederik Holle, penangkap Dipati Ukur adalah tiga umbul dari Priangan Timur, yaitu Umbul Sukakerta (Ki Wirawangsa), Umbul Cihaurbeuti (Ki Astamanggala) dan Umbul Sindangkasih (Ki Somahita). Sedangkan dalam Naskah Dipati Ukur yang ada di Leiden dan ditulis oleh R.A. Sukamandara, disebutkan bahwa sang dipati ditangkap oleh pasukan yang dipimpin oleh Adipati Kawasen, Bagus Sutapura.
Ada hal yang bisa dipetik dari kisah Dipati Ukur ini adalah keberanian dan sikap kritis Dipati Ukur melawan Belanda di Batavia atau Mataram. Memegang keteguhan prinsip yang dianggapnya benar, terlepas dari versi benar atau salah yang dilabelkan pada diri Dipati Ukur.
Itulah sejarah singkat Dipati Ukur yang pemberani dan mempunyai sikap kritis dalam dirinya. Apalah arti sebuah penafsiran seorang pemberontak atau pahlawan tergantung penafsiran masing-masing yang berbeda. Namanya sudah abadi dalam setiap ingatan manusia dan tertera menjadi nama sebuah jalan di kawasan pendidikan di kota Bandung.
Dalam rangkaian peristiwa yang saling jalin menjalin tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehormatan dan keserakahan adalah dua hal yang berlainan. Meskipun balasannya kematian, kehormatan mesti ditegakkan. Sedangkan keserakahan, meskipun tawarannya adalah kebahagiaan, mesti bisa dijauhkan. Bukan hanya demi kebaikan yang sesaat dirasakan, namun juga demi catatan sejarah yang abadi sebab dituliskan, dan menjadi bacaan banyak insan di setiap zaman.
Keserakahan memang tidak mengenal asal bangsa, namun bersemayam di jiwa-jiwa haus kuasa sehingga ia menjelma menjadi raksasa penyiksa yang bahkan bisa saja berasal dari satu kelompok bangsa dan bahasa yang sama. Ingat saja, pemangsa bisa hadir dari orang terdekat yang berada di sekeliling kita. Jangan berlebihan curiga, cukup mawas diri dan selalu waspada.
Referensi
- Danasasmita,Saleh, Yoseph Iskandar, Enoch Atmadibrata. 1983/1984. "Rintisan Penelusuran Masa Silam, Sejarah Jawa Barat, 4". Jawa Barat: Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemprov Daerah Tingkat I.
- Ekadjati, S. Edi. 1979. "Cerita Dipati Ukur Karya Sastra Sejarah Sunda Penelusuran Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846 – 2010". Bandung: Pustaka Jaya.
- Lasmiyati. 2016. "Dipati Ukur dan Jejak Peninggalannya di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (1627-1633)". Jurnal Patanjala Vol. 8 No. 3 September 2016: 381- 396 hal.381-396. neliti.com Diakses 5 Nopember 2023 [PDF] Download.
- Lubis, Nina Herlina., Mumuh Muhsin, Etty S Dyanti, Awaludin Nugraha, Mihtahul Falah. 2008."Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa". Sumedang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Sumedang.
- Priyadi, Soegeng. 2001. “Perdikan Cahyana”, Jurnal Penelitian Humaniora. Vol. XIII No. 1 Februari 2001, hlm. 89-100.
- Sutjianingsih. 1986. "Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung ke Batavia". Jakarta: Depdikbud Direktorat Jarahnitra Proyek IDSN.
- Setiawan, A dan U, Syahbudin. 2006. "Dipati Ukur Ksatria dari Pasundan". Cerita Rakyat Jawa Barat. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumantri, Lily. 1973. "Hari Jadi Kabupaten Bandung, 20 April 1641". tt.