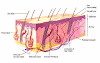|
| Naskah Lontar Kidung Sundayana |
[Historiana] - Oleh Alam Wangsa Ungkara -Naskah Sunda kuno adalah salah satu peninggalan budaya yang mencerminkan kecerdasan, kreativitas, dan kepekaan spiritual masyarakat Sunda masa lampau. Keberadaannya menjadi bukti bahwa tradisi literasi di Tatar Sunda telah berkembang sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum pengaruh kolonial Barat masuk ke Nusantara. Naskah-naskah ini tidak hanya sekadar dokumen tekstual, tetapi juga artefak sejarah yang menyimpan informasi tentang kehidupan sosial, politik, agama, dan seni masyarakat Sunda. Artikel ini akan mengupas sejarah munculnya naskah Sunda kuno, proses perkembangannya, dan analisis mendalam tentang signifikansinya dalam konteks budaya dan sejarah.
Awal Mula Kemunculan Naskah Sunda Kuno
Tradisi penulisan di wilayah Sunda dapat ditelusuri kembali ke masa Kerajaan Tarumanegara (abad ke-4 hingga ke-7 Masehi), salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat. Bukti awal kemampuan menulis terlihat pada prasasti-prasasti seperti Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, dan Prasasti Tugu, yang ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti-prasasti ini menunjukkan pengaruh kuat budaya India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Namun, pada masa ini, bahasa dan aksara yang digunakan belum mencerminkan identitas Sunda secara spesifik, melainkan lebih bersifat kosmopolitan dalam konteks Nusantara.
Perkembangan yang lebih jelas menuju naskah Sunda kuno mulai terlihat pada masa Kerajaan Sunda (abad ke-8 hingga ke-16), yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Pada periode ini, aksara Sunda kuno mulai terbentuk sebagai adaptasi dari aksara Kawi, yang sendiri merupakan turunan dari aksara Pallawa. Aksara ini digunakan untuk menulis naskah-naskah dalam bahasa Sunda Kuna, sebuah dialek yang menjadi cikal bakal bahasa Sunda modern. Salah satu naskah penting dari masa ini adalah Carita Parahyangan, yang diperkirakan ditulis pada abad ke-16. Naskah ini berisi narasi sejarah, mitologi, dan genealogi Kerajaan Sunda, termasuk kisah-kisah tentang Prabu Siliwangi, seorang raja legendaris yang menjadi simbol kejayaan Pajajaran.
Media, Teknik Penulisan, dan Isi Naskah
Naskah Sunda kuno umumnya ditulis di atas lontar, yaitu daun kelapa yang dikeringkan dan dipotong menjadi lembaran-lembaran tipis. Proses penulisannya melibatkan penggunaan pisau kecil atau stylus untuk mengukir aksara pada permukaan lontar, diikuti dengan pengolesan tinta alami yang terbuat dari campuran arang, getah tumbuhan, atau bahan organik lainnya. Teknik ini menunjukkan keterampilan tinggi masyarakat Sunda dalam pengolahan bahan dan seni kaligrafi. Pada periode yang lebih belakangan, terutama setelah masuknya pengaruh Islam, penggunaan kertas mulai ditemukan, terutama di kalangan elit yang terhubung dengan jalur perdagangan internasional.
Isi naskah Sunda kuno sangat beragam dan mencerminkan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Naskah seperti Sanghyang Siksa Kandang Karesian (1518 M) berisi ajaran moral, filsafat hidup, dan panduan berperilaku bagi masyarakat Sunda. Naskah ini ditulis dalam bahasa Sunda Kuna dan menggunakan aksara Sunda kuno, menunjukkan bahwa tradisi literatur sudah menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial. Selain itu, ada pula naskah seperti Kutara Manawa, yang mengatur hukum adat dan tata cara penyelesaian konflik, serta naskah-naskah sastra seperti Pantun Sunda yang berisi cerita epik dan puisi tradisional.
Pengaruh Islam dan Transformasi Tradisi Tulis
Masuknya Islam ke wilayah Sunda pada abad ke-15 dan ke-16, melalui Kesultanan Banten dan Cirebon, membawa perubahan signifikan dalam tradisi penulisan. Aksara Sunda kuno perlahan mulai digantikan oleh aksara Pegon, yaitu aksara Arab yang disesuaikan untuk menulis bahasa lokal. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui fase peralihan di mana pengaruh Hindu-Buddha dan Islam bercampur dalam karya-karya tulis. Contohnya adalah naskah Sewaka Darma, yang mengandung unsur-unsur lokal Sunda sekaligus ajaran Islam, serta Sulanjana, yang menceritakan kisah mitologis dengan nuansa religius baru.
Transformasi ini juga terlihat pada perubahan tema naskah. Jika sebelumnya naskah-naskah lebih banyak berfokus pada mitologi dan hukum adat, pada masa Islam banyak naskah yang berisi ajaran tasawuf, sejarah kesultanan, dan nasihat agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas budaya Sunda dalam menerima dan mengadaptasi pengaruh baru tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas aslinya.
Pembahasan Mendalam: Signifikansi dan Tantangan Naskah Sunda Kuno
Naskah Sunda kuno memiliki nilai historis yang tak ternilai karena menjadi sumber primer untuk memahami dinamika masyarakat Sunda sebelum era modern. Dari segi politik, naskah-naskah ini mengungkapkan struktur kekuasaan di Kerajaan Sunda, termasuk hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Majapahit dan Sriwijaya. Misalnya, Carita Parahyangan menyebutkan interaksi antara Pajajaran dan kerajaan lain, memberikan gambaran tentang geopolitik Nusantara pada masa itu.
Dari perspektif agama, naskah-naskah ini mencatat transisi kepercayaan masyarakat Sunda dari animisme dan Hindu-Buddha menuju Islam. Sanghyang Siksa Kandang Karesian, misalnya, tidak hanya berisi ajaran moral, tetapi juga petunjuk tentang hubungan manusia dengan alam dan kekuatan gaib, yang mencerminkan kosmologi Sunda kuno. Ketika Islam masuk, terjadi sintesis unik antara tradisi lokal dan ajaran baru, yang terlihat dalam penggunaan simbol-simbol Islam dalam konteks budaya Sunda.
Secara linguistik, naskah Sunda kuno adalah harta karun bagi studi filologi. Bahasa Sunda Kuna yang digunakan dalam naskah-naskah ini menunjukkan perbedaan fonetik, morfologi, dan sintaksis dibandingkan bahasa Sunda modern. Misalnya, penggunaan kata-kata seperti "hyaang" (dewa) atau "kabuyutan" (tempat suci) menunjukkan kosakata yang kini jarang digunakan, tetapi memberikan petunjuk tentang evolusi bahasa. Studi tentang aksara Sunda kuno juga membantu memahami hubungan budaya antara Sunda, Jawa, dan Bali, yang memiliki tradisi aksara serupa.
Namun, signifikansi naskah-naskah ini diimbangi oleh tantangan besar dalam pelestariannya. Banyak naskah yang rusak akibat kondisi lingkungan, seperti kelembapan dan serangan serangga, terutama karena lontar bersifat organik dan rentan terhadap degradasi. Selain itu, selama masa kolonial dan pasca-kemerdekaan, kurangnya perhatian terhadap dokumentasi sistematis menyebabkan banyak naskah hilang atau hanya tersisa dalam bentuk salinan yang kadang tidak akurat. Saat ini, upaya pelestarian melalui digitalisasi dan penelitian intensif oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional dan universitas lokal menjadi langkah penting untuk menyelamatkan warisan ini.
Kesimpulan
Munculnya naskah Sunda kuno adalah bagian dari perjalanan panjang peradaban Sunda yang kaya akan tradisi literasi. Dari prasasti Tarumanegara hingga naskah-naskah era Pajajaran dan masa Islamisasi, warisan ini mencerminkan kemampuan masyarakat Sunda untuk menciptakan, beradaptasi, dan melestarikan identitas budayanya di tengah berbagai pengaruh. Naskah-naskah ini bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga simbol ketahanan budaya yang terus relevan hingga kini. Dengan melanjutkan upaya pelestarian dan kajian mendalam, kita dapat memastikan bahwa jejak peradaban Sunda ini tetap hidup untuk generasi mendatang.
Daftar Referensi
- Ekadjati, Edi S. (1988). Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan. Bandung: Yayasan Kebudayaan Nusantara.
- Noorduyn, J., & Teeuw, A. (2006). Three Old Sundanese Poems. Leiden: KITLV Press.
- Pudjiastuti, Titik. (2007). Naskah dan Filologi: Studi Naskah Sunda Kuna. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.
- Saleh, Hasanuddin WS. (1992). Tradisi dan Transformasi Budaya Sunda. Bandung: Penerbit ITB.