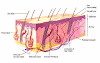|
| Lokasi Ilustrasi: chingnengbin.blogspot.co.id |
Kehidupan masyarakat kuno di tatar Sunda disebut Buhun, ya artinya kuno. Agama Sunda buhun disebut-sebut sebagai suatu sistem kepercayaan dan keyakinan manusa Sunda kuno, Sunda Buhun. Akhirnya terciptalah sebuah "nama" agama Sunda Buhun. Agama Sunda Buhun, Keyakinan Tertua Yang Pernah Ada di Dunia. Sementara istilah agama adalah serapan dari luar, yaitu dari bahasa sanksekerta.
Keyakian urang Sunda buhun sampai saat ini masih hangat dan menarik untuk diperbincangkan, bahkan ada yang menyebut ajaran "Sunda Wiwitan" Meskipun Sunda Wiwitan sebagai penamaan 'baru' dalam bahasa Sunda baru, yang bermakna permulaan (wiwitan).Para filolog, seperti Ekadjati (2005), Atja dan Saleh Danasismita (1987) menyebutnya ajaran "Jati Sunda" atau "Sunda Wiwitan".
Istilah "agama Jati Sunda" ditemukan didalam naskah Carita Parahiyangan. Naskah tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 1580 masehi, menurut CM. Pleyte 1500 M. Istilah "jati" atau wiwitan" memiliki makna yang sama, yaitu mula, pertama, asli, dengan demikian pengertian agama "Jati Sunda" atau "Sunda Wiwitan"[1] bermakna agama (urang Sunda) asli atau tulen. (Ekadjati: 2005, hal. 181).
Di Indonesia, setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli sejak zaman prasejarah, seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; Sunda Wiwitan aliran Madrais, juga dikenal sebagai agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; agama Buhun di Jawa Barat; Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim, agama asli Batak; agama Kaharingan di Kalimantan, kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Sulawesi Utara, Tolottang di Sulawesi Selatan, Wetu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dan lain-lain.
Kini ada yang membenturkan istilah agama asli dan agama impor. Kecenderungan ini bersifat negatif dan adanya sikap arogansi antar pihak yang berseberangan, hingga ngotak-ngatik istilah bahasa. Adanya keberatan kata agama asli, "bahawa tidak ada yang asli di Indonesia, bahkan kata asli sendiri bukan dari Nusantara". Kondisi keknian kita sering mendengar isitlah atau terminologi bahasa sendiri disangkutpautkan dengan agama. Wow.. mengapa demikian? bahasa sebenarnya hanya sebuah tools yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud dirinya kepada orang lain, tanpa ada kepentingan agama atau kepercayaan tertentu.
Istilah asli muncul dalam perkembangan wacana belakangan ini, karena kita berbahasa Indonesia. Bahasa kita adalah serapan dari berbagai bahasa dunia, maka tak pelak kata "asli" yang berasa dari bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia.Sedangkan dalam ejaan lama kita menggunakannya "tulen" dan orang Sunda menyebutnya "pituin" bukan asli. Baiklah, kita tidak membahas mengenai istilah bahasa secara etimologis. dan kita sepakati bahawa yang dibahas dalam artikel ini adalah Sunda Buhun sebagai sistem kepercayaan yang telah ada di Nusantara.
Penelusuran sumber sejarah
Beberapa perbedaan penafsiran tentang inti dan pemahaman Sunda sebagaimana diatas, disebabkan adanya alur sumber informasi yang berbeda.- Pertama sumber yang berasal dari tutur tinular, pada umumnya di sampaikan secara lisan oleh para penganut ajaran Sunda Wiwitan, namun masih sangat tertutup bagi orang-orang diluar penganut ajaran tersebut.
- Kedua, penemuan sejarawan, filolog, arkeolog, akhli ke purbakalaan yang menafsirkan dari temuan ilmiah, dan hasil uji mengggunakan data ilmu pengetahuan, seperti naskah-naskah; prasasti-prasasti dan lain sebagainya.
Hal yang tidak mustahil, gelapnya ajaran Ki Sunda disebabkan Ki Sunda pada masa lalu kurang menyukai untuk mendokumentasikan ajajarannya yang dianggap tabu (pamali), sementara ajaran lainnya yang juga berkembang mendokumen tasikan ajarannya dalam bentuk naskah maupun prasasti.
Hal paling mungkin mengambil kesimpuan para ahli, yang menyebutkan, bahwa: “ajaran yang berkembang dimasyarakat belum tentu sama dengan ajaran yang dianut keratonnya”. Karena penghuni keraton pada umumnya sudah bersentuhan dengan budaya luar, yakni sejak masa lengsernya Aki Tirem di Salakanagara.
Tempat Suci Ageman Sunda Buhun
Sumber-sumber sejarah menunjukkan adanya kepercayaan asli Sunda yang berlangsung lama didalam kehidupan masyarakat Sunda, baik sesudah maupun sebelum masa Pajajaran terbentuk. Naskah Carita Parahyangan mendeskripsikan adanya Kaum Pendeta Sunda yang menganut ageman asli Sunda (Nu Ngawakan Jati Sunda). Mereka mempunyai tempat kegiatan, atau semacam tempat suci yang bernama Kabuyutan Parahyangan, suatu hal yang tidak dikenal dalam agama lain, bahkan dibedakan dengan Kabuyutan Lemah Dewasasana, yang dianggap sebagai pusat kegiatan ke agamaan Buddha.Naskah Carita Parahyangan menceritakan mengenai kepercayaan umum raja-raja Sunda-Galuh adalah Sewabakti ring Bataran Upati dan berorientasi kepada kepercayaan asli Sunda. Selain naskah Carita Parahyangan, keyakinan Jati Sunda pada masa lampau dikisahkan para prepantun Bogor, seperti oleh Aki Buyut Baju Rambeng. Menurut Ki Panjak (1970), Pantun Bogor (Pajajaran Tengah) berisi tentang Uga yang hanya dapat dibaca (dipahami) kisahnya jika dikalbunya tertanam rasa kasundan. Masalah ini dikisah didalam kisah Curug Si Pada Weruh, bahwa :
Saacan urang Hindi ngaraton di Kadu Hejo ogeh, karuhun urang mah geus baroga agama, anu disarebut agama Sunda tea. (Sebelum orang Hindi (Hindu-India) ber tahta di Kadu Hejo pun, leluhur kita telah memiliki agama, yakni yang disebut agama Sunda).Kisah dan istilah urang Hindi di Kaju Hejo dimaksudkan kepada para penguasa Salakanagara pasca pelengseran Aki Tirem lebih tepatnya jika disebutkan untuk Dewa Warman, pengganti Aki Tirem.
Mengenai penggantian Aki Tirem oleh Dewa warman ada pula yang memahami sebagai apa yang disimbulkan didalam kisah Aji Saka dan Dewata Cengkar. Aji Saka dilambangkan sebagai seorang pemuda sakti yang berwajah tampan, sedangkan Dewata Cengkar dilambang sebagai seorang buta (cakil). Aji Saka dianggap budaya baru beragama, mewakili pendobrak tradisi pribumi (Aki Tirem). Oleh karenanya para pendatang itu sendiri menggambarkan dirinya sebagai manusia tampan, agar menarik simpati, sedangkan Dewata Cengkar mewakili entitas pribumi dilambangkan sebagai sesuatu yang buruk, agar dijauhi.
Demikian lah hukum penulisan sejarah, siapa yang kalah diniscayakan berposisi sebagai yang buruk, sedangkan yang menang adalah yang baik. Sama halnya dengan mengisahkan sejarah jaman orde lama oleh para penulis orde baru, yang selalu di posisikan sebagai si ‘salah’, bertujuan agar rezim orde baru memiliki legalitimasi, atau dukungan dari rakyat.
Pada masa Aji Saka terjadi pergantian penguasa dan status wilayah, dari nama kota yang dipimpin seorang penghulu (Aki Tirem) menjadi kerajaan yang dipimpin seorang raja bernama Dewawarman. Kisah kerajaan Salakanagara pada akhirnya dianggap sebagai kota dan kerajaan tertua di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara. Pada masa ini pula diyakini sebagai awal mula kebudayaan Nusantara mulai bersentuhan dengan budaya dari India.
Peninggalan Salakanagara, berikut kisah Aji Saka dan Dewata Cengkarnya sangat dimungkinkan terkait dengan keberadaan Krakatau. Pada masa itu disebut sebagai “Nusa Apuy”. Salakanagara pada masa Tarumanagara, khususnya pada masa kejayaan Purnawarman sudah menjadi negara dibawah daulat Tarumanagara. Salakanagara, berikut kisah Dewata Cengkar tentunya habis dimusnahkan Gunung Krakatau, yang telah beberapa kali mengeluarkan letusan dahsyat. Kedahsyatan Letusan Gunung Krakatau antara lain ditemukan didalam cuplikan tulisan dari Kitab Raja Purwa, dibuat oleh pujangga Jawa dari Kesultanan Surakarta, Ronggo Warsito. Salinan kitab itu masih tersimpan rapi di Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Cuplikan dari Kitab tersebut bertuliskan:
“Seluruh dunia terguncang hebat, dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai, tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api ‘Gunung Kapi’ melainkan semakin mengobarkannya, suaranya mengerikan, akhirnya ‘Gunung Kapi’ dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam kebagian terdalam dari bumi”Kitab tersebut diterbitkan tahun 1869 atau 14 tahun sebelum letusan Krakatau (Inggris: Krakatoa volcanoes) pada 27 Agustus 1883. Penyebutan “Gunung Kapi” atau dalam bahasa Sunda “Nusa Apuy” tak banyak dikenal pada periode itu, sehingga tulisan Ronggowarsito dianggap membingungkan banyak kalangan. Namun, deskripsi berikutnya dalam buku itu semakin mirip dengan peristiwa tsunami saat Krakatau meletus pada 27 Agustus 1883:
Air laut naik dan membanjiri daratan, negeri di timur Gunung Batuwara sampai Gunung Raja Basa dibanjiri oleh air laut, penduduk bagian utara negeri Sunda sampai Gunung Raja Basa tenggelam dan hanyut be serta semua harta milik mereka.Kemudian dalam edisi kedua yang diterbitkan pada 1885 atau dua tahun setelah letusan Krakatau, Ronggowarsito menulis penanda tahun dan deskripsi lokasi Gunung Kapi yang bisa dipastikan adalah Krakatau, pernah meletus sebelum tahun 1883. Naskah tersebut mengungkapkan :
”di tahun Saka 338 (416 Masehi) sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuwara yang di jawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten baru…”.Masyarakat dan para sejarawan banyak mempersepsi agama Sunda buhun dari agama yang dianut keratonnya, seperti Tarumanagara yang meninggalkan prasasti, atau menarik kesimpulan dari tradisi yang dilakukan orang Sunda dalam ke sehariannya dianggap sama dengan saudara-saudaranya yang beragama baru (Hindu atau Buddha), apalagi sejarah ditatar Pasundan, sejak Dewawarman I berkuasa bersentuhan dengan agama para pedagang India. Tapi jika ditelusuri dan dipilah perkembangan agama yang dianut keraton dengan yang dianut rakyatnya, niscaya akan ditemukan perbedaannya. Sampai saat ini para penganut Sunda Wiwitan sangat tidak memahami tradisi Hindu maupun Buddha.
Sumber yang berasal dari keterangan Faxian atau Fa-Hsien, pendeta Buddha dari China, dalam buku berjudul Fa-Kao-Chi, menjelaskan kondisi sosial kemasyarakatan di ibukota Tarumanagara. Menurutnya, selain banyak penganut Hindu juga masih banyak penduduk yang menganut agama leluluhurnya. Contoh yang kedua, pada masa Rajaresi, Raja Tarumanagara kedua (diperkirakan tahun 382 masehi), pada masa itu pemerintahannya berupaya merubah keberagamaan masyarakat, dari agama nenek moyangnya menjadi agama yang dianut Rajaresi, namun masih banyak penduduk disekitar kerajaan yang tetap menganut agama nenek moyangnya[2].
 |
| Lukisan Fa Hsien (Faxian) Sumber: timetoast.com |
Pengecualiannya terjadi pada masa penyatuan Sunda dan Galuh, atau banyak juga yang menyebutkan masa Pajajaran. Penyatuan entitas Sunda dengan Galuh mulai cair dan menjadi hanya sebutan Sunda pada abad ke-16. Pada masa penyatuan Sunda dan Galuh nampak ada pembauran keyakinan keraton dengan keyakinan rakyat, sebagai mana ditulis dalam naskah Kawih Paningkes, yang menerangkan telah kembalinya keraton dan masyarakat Sunda menganut agama asli (leluhur) urang Sunda.
Pada masa kerajaan Sunda dan Galuh sampai dengan Pajajaran Sirna Hing Bumi Pasunda, masyarakat Sunda dan keraton sudah mulai nampak kebersamaan dalam beragama, namun pengaruh dari agama Buddha dan Hindu masih ada dan masih melekat. Pengaruh demikian dicatat dalam Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian yang banyak menjelaskan tentang pedo-man hidup Ki Sunda pada masa itu (Kundangeun Urang Reya). Naskah ini mengakui adanya ajaran leluhur dan menyebutkan adanya Batara Seda Niskala, yang dianggap Yang Hak dan Yang Wujud, bahkan didalam Hirarki Pembaktian, yang disebut Dasa Perbakti, menempatkan Hyang diatas Dewa. Penemuan Tuhan semacam keyakinan terhadap Hyang bagi masyakat Sunda lama bukan penemuan baru, namun dilingkungan keraton keyakinan terhadap sesuatu yang maha tinggi pernah kasilih setelah masuknya budaya dari luar.
Terpengaruh India
Kepercayaan agama Hindu dan Budha mengenal adanya istilah yang Gaib lainnya, yakni dewa-dewa. Panteon Hindu ini mempunyai cara hidup dan tempat tersendiri diluar kehidupan manusia, yakni di nirwana atau sorga. Dewa-dewa dalam agama Hindu jumlahnya banyak (politheis) dan memiliki fungsi dan tugas masing-masing.Dalam buku Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat (1983-1984), yang banyak merujuk kedalam naskah Carita Parahyangan disebutkan, bahwa pada masa Salakanagara dapat diduga bahwa agama resmi negara adalah agama Siwa, termasuk di dalamnya madhab Ganapatya (pemuja Ganesa), mengingat Dewawarman I dianggap asli keturunan dari India, sedangkan pada masa Tarumanagara, seperti nampak dari prasasti peninggalan masa Purnawarman, menganut agama Wisnu, termasuk madzhab Saura (Pemuja Surya). Anutan terhadap madzhab masing masing berhubungan dengan keyakinan, bahwa raja adalah titisan Wisnu yang menjaga dan melihara ketertiban Jagat raya. Di tatar Sunda yang disebut kan titisan Sanghyang Wisnu adalah Prabu Dharmasiksa. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam naskah Carita Parahyangan, yaitu:
Diganti ku Sang Rakean Darmasiksa, titisan Sanghiang Wisnu, nyaeta nu ngawangunsanghiang binajapanti. Nu ngajadikeun para kabuyutan ti sang rama, ti sang resi, ti sang disri, ti sang tarahantina parahiangan."Tina naon berkahna?" Ti sang wiku nu mibanda Sunda pi tuin, mituhu Sanghiang Darma, ngamalkeun Sanghiang Siksa. (Atja : 1968).Banyak pula raja-raja dahulu yang menganggap dirinya keturunan Dharmaraja, sehingga menggunakan gelar Dharma untuk nama nobatnya. Kisah Dharmaraja dapat ditelusuri dari kisah Satria Piningit dan Ratu Adil. Sumber ajaran ini berasal dari Kitab Tantu Pa Gelaran. Kitab ini mengisahkan tentang Siwa atau Batara Guru nu ngayuga Dewa Dharmaraja. Keduanya memiliki kemiripan dalam bertapa dan memancarkan kebajikan-kebajikan yang bersifat ilahiyah. Kelak ratu Adil akan muncul da lam wujudnya sebagai resi. Inilah yang menunjukan adanya pengaruh India didalam sistem kepercayaan di wilayah Pasundan.
Pada masa selanjutnya, didalam Naskah Sanghiyang Siksa Kanda Ng Karesian tersurat jejak keyakinan agama Siwa dan Budha sekaligus, seperti pada kata :
Hong kara namo sewa ya baktining huluan di Sanghiang Panca Tatagata ... Panca ngaran ing lima, tata ma ngaran ing sabda, gata ma ngaran ing raga. (sesungguhnya puji dan sembahku untuk Siwa, baktiku kepada Sanghyang Panca Tatagata .... Panca berarti lima, tata berarti ucapan, gata berarti wujud).Dari naskah diatas nampak penggunaan simbol-simbol Hindu dengan mengistilahkan Siwa, serta agama Buda Mahayana. Tataga dalam agama Buddha adalah gelar untuk Buddha. Panca Tataga adalah lima orang Dyani Buddha atau Buddha yang merenung sebagai Lokapala, pelindung dunia. Paradigma ini tetap hidup dan tertransformasikan kedalam istilah Buana Panca Tengah, untuk istilah bumi atau dunia. Jejak lainnya saat ini ada dalam pemahaman tentang kalimat Opat Kalima Pancer (pengaruh Kawruh Jawa), seperti dalam pepatah orang tua:
Coba riksa anu opatnu jadi bakal manusabumi, geni, banyu jeung angin.Bumi metukeun cahaya hideung, nu nyata jadi pangucap. Geni metukeun cahaya beureum, nu nyata jadi panguping. Angin metukeun cahaya koneng, nu nyata jadi pangangseu. Banyu metu keun cahaya bodas, nu nyata jadi paningal.
Nu metukeun cahaya hideung, tina bumi malaikat sa wiah. Nu metukeun cahaya beureum, tina geni malai kat tamarah. Nu metukeun cahaya koneng, tina angin na malaikat mutmainah, nu metukeun cahaya bodas, tina banyu malaikat loamah. Anu opat ngalebur ngaja di hiji, ngajadi papancer ning manusa.
(Coba periksa yang empat cikal bakal manusia, tanah, api, air dan angin. Tanah mengeluarkan cahaya hitam, menjadikan bisa mengucap. Api mengeluarkan cahaya merah, yang menjadikan bisa mendengar. Angin mengeluarkan cahaya kuning, menjadikan bisa mencium. Air yang mengeluarkan cahaya putih, yang menjadikan bisa melihat.
Yang melahirkan cahaya hitam dari bumi malaikat sawiah. Yang melahirkan cahaya merah dari api ada lah malaikat tamarah. yang melahirkan cahaya kuning dari angin adalah malaikat loamah. Yang melahirkan cahaya putih dari air adalah malaikat loamah. Yang empat melebur menjadi satu, menjadi pertandanya manusia).Paradigma tentang kalimat diatas diabadikan dalam setiap gerak hidupnya, seperti yang diabadikan dalam bentuk jurus Tepak Hiji dalam Ilmu Silat Cimande, jurus empat (mata angin) di tambah satu pancernya (tengah), atau opat kalima pancer (empat yang kelimanya pancer). Pada masa lalu, maksud yang sama menunjukkan lima huruf didalam keperca yaan Hindu, yang disebut panca aksara, yaitu Na, Mo, Si, Wa, Ya. Aksara tersebut dianggap perwujudan Siwa :
Tentang naskah Sanghyang Siksa Kanda ng Karesian dimaksud, selengkapnya sebagai berikut :
- NA Siwa sebagai Iswara Di timur
- MO Siwa sebagai Brahma Di selatan
- SI Siwa sebagai Mahadewa Di barat
- WA Siwa sebagai Wisnu Di utara
- YA Siwa sebagai Siwa Di tengah (Pancer)
Lamun pahi kaopeksa sanghyang wuku lima (dina) bwa na, boa halimpu ikang desa kabeh. Desa kabeh ngara nya: purba, daksina, pasima, utara, madya. Purba, ti mur, kahanan Hyang Isora, putih rupanya; daksina, ki dul, (kahanan Hyang Brahma, mirah rupanya; Pasima, kulon) kahanan Hyang Mahadewa, kuning (rupanya); utara, lor, kaha nan Hyang Wisnu, hireng rupanya; madya, tengah, kahanan Hyang Siwah, (aneka) warna rupanya. Nya mana sakitu sanghyang wuku lima dina bwana. (Kalau terpahami sanghyang wuku lima di bumi tentu semua tempat menyenangkan. Tempat itu disebut: purwa, daksina, pasima, utara, madya. Puwa yaitu timur tempat Hyang Isora, putih warnanya. Daksina yaitu selatan, tempatHyang Brahma merah warnanya. Pasima yaitu barat, tempat Hyang Mahadewa kuning warnanya.Utara tempat Hiyang Wisnu hitam warnanya Madya di tengah tempat Hyang Siwa aneka macam war na. Yaitulah wuku lima di bumi).Masyarakat dahulu meyakini, dari sorga para dewa mengatur dan mengawasi kehidupan manusia. Tiap pemeluk agama Hindu dan Buddha meyakini, jika mereka mengindahkan tuntunan moral dan agama maka akan masuk sorga, bersatu di alam kehidupan dewa-dewa. Sebaliknya, akan masuk neraka dan mengalami samsara, jika tekad dan perilakunya buruk.
 |
| Ilustrasi: Gunung Kukkutapadagiri Foto: gurpaon.blogspot.com |
Dari sudut pernaskahan, seperti naskah Jatiniskala mengan dung embaran mengenai ajaran keagamaan yang memperli-hatkan berbaurnya ajaran Hindu, Buddha dengan ajaran Pribumi. Naskah Jatiniskala lebih banyak menyebutkan nama-nama kuasa imajiner pribumi.
Mereka disederajatkan dengan apsari, makhluk kahyangan, pendamping para Dewa. Seperti tujuh pohaci, yaitu: Pwah sri Tunjungherang, Pwah Sri Tun junglenggang, Pwah Sri Tunjunghanah, Pwah Sri Tunjungma nik, Pwah Sri Tunjungputih, Pwah Sri Tunjungbumi, Pwah Sri Tunjungbwana. Kesemuanya berada didalam kurungan dan masing-masing mempunyai apsari, yaitu: Aksari Tunjung naba, Tunjungmabra, Tunjungsiang, Tunjungkuning, Nagawali, dan Nagagini. Kemudian ada juga apasari Manikmaya, Maya lara, dan lainnya.
Dari uraian di atas memang kedua agama di atas dikenal dalam kehidupan masyarakat Sunda Buhun, bahkan diabadikan didalam naskah-naskahnya. Namun perlu juga dikaji tentang silib, sampir, siloka dan apapun yang tersirat didalam setiap kalimatnya lebih dalam. Seperti dari naskah Sanghiyang Siksa Kandang Karesian (1518 M), tentang Dasa (sepuluh) Perbakti yang menempatkan hirarki Hiyang diatas Dewa. Nakah tersebut menyebutkan, bahwa "...mangkubumi bakti di ratu, ratu bak ti di dewata, dewata bakti di hiyang..." (mangkubumi tunduk kepada raja, raja tunduk kepada dewata, dewata tun duk kepada Hiyang) (Danasamita dkk. 1987: 74,96). Hal ini mengandung makna, bahwa hirarki Hyang atau Sang Hyang Tunggal tidak sama dengan Siwa (dewa), Sanghyang Wenang tidak sama dengan Brahma (dewa).
Sanghyangg Wening tidak sama dengan Wisnu (dewa). Oleh karena itu, didalam cara memahami konsepsi ajaran Jati Sunda atau Sunda Buhun, dan juga Sunda Wiwitan, tidak dapat dicampur adukan dengan Panteon lain. Konon menurut Juru Pantun: “ti baheula mula, urang sunda mah geus miboga Hyang Tunggal, nu teu bisa dibandingkeun jeung ciptaannana”.
Konsep Hyang dalam Sunda Buhun
Hyang, Hiyang atau Sanghiyang didalam Ensiklopedia Sunda, ditujukan untuk menyebutkan para penghuni kahyangan. Hal yang tentunya berbeda dalam cerita wayang, karena kahyangan di huni oleha para dewa. Menurut pendapat lain, Parahyangan adalah istilah untuk tempat tinggalnya para Hyang, sedangkan Nirwana tempat tinggal para Dewa.Yang Maha kuasa menurut kepercayaan Sunda buhun adalah Sabghyang Keresa, yang menghendaki atau Sang Hyang Karsa atau sang Mahapencipta, disebut juga Batara Tunggal atau Batara Seda Niskala (yang ghaib). Semua Dewa yang datang kemudian diposisikan berada dialam Niskala, sedangkan Hiyang berada di alam Jatiniskala. Oleh karena itu didalam Dasa Prebakti, Sanghiyang lebih tinggi hirarkinya dari Dewa-dewa atau Batara.
Istilah Sanghyang adakalanya digunakan pula untuk menyebut orang atau makhluk yang dihormati, seperti Sanghiyang Lutung Kasarung, Sanghiyang Sri, Sanghiyang Borosngora dan lain-lain. Namun bisa saja sebutan itu untuk menyebutkan pengejawantahan dari Hiyang, yang memang tidak berwujud.
Perkembangan selanjutnya menurut Ekadjati (2005), konsep banyaknya dewa-dewa (politheis), pada masa kerajaan Sunda dan Galuh menimbulkan kecenderungan untuk mengutamakan roh dan dewa (Tuhan) tertentu, namun mengabaikan dewa lainnya. Selain itu di dalam upacara keagamaan lain yang sarat tatacara, dan urutan yang ketat serta mantera-mantera yang tidak boleh salah ucap atau salah susun, dianggap kurang sesuai dengan watak agama asli leluhurnya.
Oleh karena itu mereka mencari konsep alternatif lain untuk menemukan Tuhan yang sesuai dengan karakternya yang berpindah-pindah setiap musim panen. Sehingga perlu praktis, akrab dengan alam, mengutamakan isi daripada bentuk, cara memuja dapat dilakukan dimana saja, karena Tuhan itu lebih dekat dari apapun, bahkan masih jauh urat dileher kita dibandingkan dengan Tuhan.
Bagi masyarakat Sunda waktu itu, sebongkah batu alam yang agak aneh bentuknya sudah cukup untuk dijadikan titik pusat upacara ritual. Setelah usai batu tersebut ditinggalkannya karena di tempat lain pun masih mudah memperoleh jenis batu yang sama. Modal penting untuk menjalin hubungan dengan yang Gaib adalah kesungguhan hati, kehidmatan di dalam keheningan alam sekitar. Sedangkan bongkahan batu hanya sekedar Yantra, pembantu konsentrasi, bukan sesuatu yang harus disembahnya.
Buku Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat (1983-1984, Danasasmita, kk) menyebutkan, bahwa agama Sunda pada masa Sunda kuno memiliki kitab suci yang menjadi pedoman umatnya, yaitu Sambawa, Sambada dan Winasa.
Ketiga kitab suci tersebut baru ditulis pada masa pemerintahan Rakean Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu, yang berkuasa ditatar Sunda pada periode 1175-1297 M. Kitab ini merupakan bentuk pengulangan dan penegasan, karena Prabu Darmasiksa bukanlah penganut agama Sunda yang pertama, bahkan keberadaan ageman Jati Sunda sudah diketahui pada masa Aki Tirem, untuk kemudian kasilih dan bersentuhannya dengan budaya dari India. Namun memang setelah masa Prabu Darmasiksa agama Sunda Wiwitan menjadi agama resmi kerajaan.
Keberadaan ageman Jati Sunda telah tercatat sejak adanya Mandala Sunda Sambawa (diperkirakan sekitar muara Sungai Cihaliwung, Bekasi sekarang). Guru Resi Tarusbawa (selanjutnya menjadi pendiri kerajaan Sunda) telah mengajarkan Ageman Jati Sunda. Nama Tarusbawa sendiri terdapat dalam Naskah Wangsakerta II: Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara, Pustaka Carita Parahyangan I Bhumi Jawa Kulwan,dan Sarwakrama Rajyarajya Galuh-Pajajaran.
Konsepsi teologis Sunda Wiwitan berbasiskan pada faham Monoteisme atau percaya akan adanya keberadaan Hyang itu gaib dan Tunggal, tidak jamak. Hyang atau Sanghiyang di dalam Ensiklopedia Sunda ditujukan untuk menyebutkan Yang Maha kuasa, menurut kepercayaan Sunda lama adalah Sang hyang Keresa (Maha Pencipta), disebut juga Batara Tunggal (Yang Esa), atau Batara Seda Niskala (Yang Gaib). Semua Dewa yang datang kemudian, tunduk kepadanya. Oleh karena nya Sanghyang dianggap memiliki hirarki tertinggi di bandingkan para dewa.
Paradigma yang menempatkan hiyang sebagai hiraki pembaktian tertinggi ditemukan, antara lain didalam naskah-naskah :
- Uraian tentang Dasa Prebakti yang ditulis didalam naskah Sanghiyang Siksa Kanda ng Karesian, yang menyebutkan: “Nihan sinangguh dasa prebakti ngaranya. Anak bakti di bapa; ewe bakti di laki; hulun bakti di pacandaan; sisya bakti di guru; wang tani bakti di wado; wado bak ti di mantri; mantri bakti di nu nangganan; nu nangga nan bakti di mangkubumi; mangku bumi bakti di ratu; ratu bakti di dewata; dewata bakti di hyang. Ya ta sinangguh dasa prebakti
ini yang disebut dasa prebakti. Anak tunduk kepada bapak; isteri tunduk kepada suami; hamba tunduk kepada majikan; siswa tunduk kepada guru; petani tunduk kepada wado; wado tunduk kepada mantri, mantri tunduk kepada nu nangganan; nu nangganan tunduk kepada mangkubumi; mangkubumi tunduk kepada raja; raja tunduk kepada dewata; dewata tunduk kepada hiyang. Ya itulah yang disebut dasa prebakti. (Dana Sasmita, dkk. 1987: 74,96)
- Naskah Paningkes, atau Naskah Panikis menyebutkan:
“...baruk da sang wiku lamun muja ka dewata langit kawikwana ma pandita lamun samadi mihdap hyang dewata hilang na kapanditaan ja kassarkon kati nong sarwa dingan trisna bala swarangan...
...katanya, jika wiku ‘pendeta’ bersamadi (memuja) dewata, hilanglang kependetaannya, karena perhatian dan kecintaannya tergeser oleh (kelakuannya) sendiri... (Ayatrohaedi, :15,33)Nakah ini berhubungan pula dengan naskah terakhir dari Sanghyang Siksa Kandang Karesyan, bahwa ketentuan ini su dah ditentukan sejak alam diciptakan oleh Batara Seda Niskala, sebagai Yang Hak dan Yang Wujud. Naskah tersebut berbunyi demikian :
Sakala batara jagat basa ngretakeun bumi niskala. Ba sana: Brahma, Wisnu, Isora, Mahadewa, Siwa. bakti ka Batara! Basana: Indra, Yama, Baruna, Kowera, Besa war ma, bakti ka Batara ! Basana: Kusika, Garga, Mestri, Pu rusa, Pata(n)jala, bakti ka Batara: Sing para dewata ka beh pada bakti ka Batara Seda Niskala. Pahimanggih keun situhu lawan preityaksa.
(Suara panguasa alam waktu menyempurnakan mayapada. Ujarnya: Brahma, Wisnu, isora, Mahadewa, Siwah, baktilah kepada Bata ra! Ujarnya: India. Yama, Baruna, Kowara, Besawarma, baktilah kepada Batara! Ujarnya: Kusika, Garga, Mestri, Purusa, Patanjala, baktilah kepada Batara! Maka para dewata semua berbakti kepada Batara Seda Niskala. Semua menemukan Yang Hak dan Yang Wujud)
- Naskah Jatiraga menyebutkan Batara Jati Niskala, sebagai kekuatan adikodrati:
Batara Jati Niskala, Tema(h)han Batara Niskala, Yata dewata niskala, Pitu racok jadi tunggal, Mari sirnanan tu.” (Batara Jatiniskala (adalah) penjelmaan Batara Niskala yakni yang besrifat gaib, tampil tujuh menjadi tunggal, demikian smuanya itu).(Darsa & Edi S. Eka djati, 2006: 129 dan 149).Sifat Hyang tercermin dari nama-nama yang diberikan kepadanya, yaitu Batara Niskala atau Jatiniskala yang bersifat gaib, Sanghyang Jatinistemen (hakikat keteguhan), didalam naskah Serat Dewa Buda disebut Sanghyang Taya. Ia menjelma menjadi tujuh sanghiyang, dengan sebutan Tujuh Guriang. Tujuh Guriang ini dapat ditemukan didalam naskah Jatiraga (koropak 422), yakni:
- Sang Hyang Ijuna Jati;
- Sang Hyang Tunggal;
- Sang Hyang Batara Lenggang Buana;
- Sang Hyang Aci Wisesa;
- Sang Hyang Aci Larang;
- Sang Hyang Aci Kumara;
- Sang Hyang Manwan (Manon).
Naskah Jatiraga menyebutkan pula:
“Berhasilah dia memerintah, pada bumi tanpa tanah, pada ruangan tanpa udara, pada siang hari tanpa matahari, pada purnama tanpa bulan, pada tiupan tanpa ngin, pada cahaya tanpa bayangan, pada angkasa tanpa langit, pada kodrat tanpa kehidupan ....” (Darsa & Edi S. Eka djati, 2006: 149).Inilah yang disimpulkan Munandar (2010 : 41), bahwa Sang Hyang Jatiniskala benar-benar bersifat niskala, tidak dapat terbayangkan, tidak dapat dikonkretkan. Kalaupun dikonkret kan harus diambil dari alam dalam wujud aslinya, “sebab aku adalah asli dan dari keaslian’, tidak perlu dirubah dalam ben tuk benda alam, yang tidak asli dan tidak jujur, sebab “aku adalah jujurnya dari kejujuran”. Sanghyang Niskala tidak muncul dalam bentuk nyata, tidak berwujud, atau tidak seperti Siwa Maha Dewa yang masih dibayangkan dalam ben tuk arca bertangan empat, memiliki mata ketiga didahi, me makai Upavita (tali kasta) naga dipuncak kepala. Sang Hyang Tunggal atau Sanghyang Jatiniskala bukan menunjukan Siwa.
Tentang dzat pencipta yang tunggal ditemukan pula didalam naskah Sang Hyang Raga Dewata, yang menuliskan :
“ ....Hanteu nu ngayuga aing, Hanteu manggawe aing, Aing ngarana maneh, Sanghiyang raga dewata..." (...Tidak ada yang menjadikan Aku, Tidak ada yang menciptakan Aku, Aku menamai diri sendiri, Sang Hiyang Raga Dewata..). (Ekadjati & Endang Undang A. Darsa 2004, 2004).Naskah tersebut menjelaskan pula tentang sifat-sifat Sang Hiyang Raga Dewata, yakni:
“ ...datang tanpa rupa, tanpa raga, tak terlihat perkataan (senantiasa) benar, rupa direka, karena ada. Akulah yangmenciptakan tetapi tak terciptakan, Aku lah yang bekerja, tetapi tidak dikerjakan, Akulah yang menggunakan tetapi tidak digunakan...” (ibid).Sifat-sifat Sang Hiyang Raga Dewata tersebut sama dengan Sang Hiyang Jatiraga atau julukan lainnya Jatniskala, Jatinistemen, atau Sang Hiyang Tunggal. (Munandar, 2010). Itulah ha kekat tertinggi dalam sistim keyakinan Sunda Buhun. Dan inilah konsep Hyang dalam agama Sunda Buhun.
Ajaran Sunda Buhun - Jati Sunda
Ajaran Jati Sunda tentang "Tri Tangtu" diajarkan di Kamandalan Sunda Sembawa. Tri Tangtu (Rama, Resi, Ratu) merupakan tiga kekuataan Purbatisti Purbajati i Bhumi Pertiwi yang menghasilkan Uga (perilaku) Ungkara (nasehat) Tangara (tanda alam), sebagai sistem pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara yang telah dipergunakan oleh para Pangagung mwah Pangluhung i Sunda Sembawa Sunda Mandala. Dalam Modul pengajaran Basa Sunda Depdiknas, 2017 menyebut Tritangtu: Sang Prabu, Sang Rama dan Sang Resi.Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) layeut tur ngalagénana pamaréntahan téh ku ayana Tri Tangtu di Buana atawa Tri Tangtu di Bumi, maksudna tilu katangtuan hirup di alam dunya: Sang Prabu, Sang Rama, jeung Sang Resi. Sang Prabu minangka lambang Wisnu, Sang Rama minangka lambang Brahma, jeung Sang Resi minangka lambang Iswara (Atja jeung Danasismita, dina Sudaryat, 2015:19).Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) sejalan dan beriningan dengan pemerintahan dengan adanya Tri Tangtu di Buana atau Tri Tangtu di Bumi, maksudnya tiga ketentuan hidup di alam dunia: Sang Prabu, Sang Rama, dan Sang Resi. Sang Prabu (Raja) sebagai simbol Wisnu, Sang Rama sebagai simbol Brahma, dan Sang Resi sebagai simbol Iswara (Atja dan Danasismita, di Sudaryat, 2015: 19).
Sang Prabu nyaéta pamingpin roda pamaréntahan (éksékutif), pamingpin formal, birokrat, pamaréntah (presidén, raja) nu miboga kawijakan. Nu jadi Prabu kudu boga falasifah “ngagurat batu” boga watek panceg, hartina taat jeung patuh kana hukum enggoning ngajalankeun pamaréntahanana, teu ngarékayasa, éstu ngadék sacékna nilas saplasna. Kudu patuh jeung taat kana hukum agama, hukum nurani, hukum adat pon kitu deui hukum positif. Lamun pamingpin taat azas, mangka komunitas nu dipingpinna bakal lumansung dina koridor anu bener.Sang Prabu adalah pemimpin roda pemerintahan (eksekutif), pemimpin formal, birokrasi, pemerintah (presiden, raja) memiliki kebijakan. Jadi dia harus memiliki Falasifah "ngagurat batu" memiliki kebiasaan konsisten, adalah taat dan patuh kepada hukum telah dijalankan pemerintah, bukan rekayasa, melakukan tindakan sebagaimana mestinya. Taat dan mematuhi hukum, hukum hati nurani, jikalau memimpin sesuai dengan adat begitupun sesuai dengan hukum positif. Jika pemimpin taat azas, maka masyarakat yang dipimpinnya berjalan di koridor yang benar.
Sang Rama nyaéta golongan masarakat anu dikolotkeun pikeun ngawakilan di lembaga legislatif. Sang Rama kudu boga filosofis “ngagurat lemah”, maksudna kudu bisa nangtukeun naon anu bisa jadikeun titincakan. Fungsi Sang Rama nyaéta ngawujudkeun kulawarga anu silih asih, silih asuh jeung silih asah atawa kulawarga anu sakinah, mawadah jeung warohmah.Sang Rama adalah golongan masarakat yang dituakan untuk wewakili di lembaga legislatif. Sang Rama harus memiliki filosofis “ngagurat lemah”, maksudnya harus bisa menentukan apa yang bisa dijadikan pijakan. Fungsi Sang Rama adalah mewujudkeun kelaarga yang silih asih, silih asuh dan silih asah atau kelaarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.
Sang Resi nyaéta golongan masarakat nu boga pancén pikeun ngokolakeun hukum agama jeung hukum darigama, hukum nagara (yudikatif). Sang Resi téh minangka simbul jalma anu jembar ku élmu panemuna, pinter tur singér, ulama, guru anu mampuh ngatik ngadidik geusan kamajuan bangsana. Sang Resi kudu miboga falasifah “ngagurat cai” tegesna tiis tengtrem dina prosés peradilan nu ngandung harti jembar nyaéta mampuh ngarojong ngadorong sangkan rahayat bisa maju sawawa jeung bangsa séjén, miboga ajén-inajén tur mandiri.Sang Resi adalah golongan masarakat yang memiliki tugas untuk mengelola hukum agama dan hukum darigama, hukum nagara (yudikatif). Sang Resi sebagai simbol manusia yang luas ilmu pengetahuannya, cerdik cendikiawan, ulama, guru yang mampu mendidik untuk kemajuan bangsanya. Sang Resi harus memiliki filosofi “ngagurat cai” jelasnya menentramkan dalam proses peradilan yang mengandung arti jembar yaitu mampu mendorong agar rakyat bisa maju dan bermartabat dihargai bangsa lain, memiliki kepribadian dan mandiri.
TANAH SUNDA
Tanah Sunda wibawa,
Gemah ripah tur éndah,
Nu ngumbara suka betah,
Urang Sunda sawawa,
Sing towéksa percéka,
Nyangga darma anu nyata,
Seuweu Pajajaran,
Muga tong kasmaran,
Sing tulatén jeung rumaksa,
Miara pakaya,
memang sawajibna,
Geten titén rumawat tanah pusaka.
Geura hég lenyepan, éta konsép falasifah hirup jeung ahéngna budaya Sunda anu digambarkeun dina rumpaka di luhur, sakitu tohagana, piraku urang teu hayang nuluykeun, sakurang-kurangna ulah opénan pikeun ngaruksak budayana. Kapanan alat budaya téh, nya basa téa. Hartina, lamun basana kapiara kalawan hadé tur ajeg, budayana ogé moal jauh ti kitu. Urang Sunda sawawa, hartina teu kudu hélok ku budaya batur, da budaya Sunda gé hadé, sawawa jeung séké sélér bangsa séjén. Buktina naskah-naskah Sunda heubeul pada ngaguar ku bangsa séjén, kayaning Perancis, Jepang, geus puguhning ari Walanda mah. Kasenianana ogé pada mikaresep ku bangsa deungeun. Loba urang asing ngadon dialajar kasenian Sunda, boh di urang boh di nagarana.
Simaklah baik-baik, ini konsep filsafat hidup dan agungnya budaya Sunda yang digambarkan dalam bait di atas, dengan tegasnya, masa kita tidak ingin melanjutkan, sekurang-kurangnya jangan melakukan tindakan yang merusak budayanya. Sementara alat budaya, yaitu bahasa. Hartinya, jika bahasanya terpelihara dengan baik dan ajeg, budayanya juga tkkan jauh semerti tiu. Orang Sunda sawawa, hartinya jangan mengikuti budaya asing, karena budaya Sunda juga adiluhung, bermartabat dan sejajar dengan bangsa lain. Buktinya naskah-naskah Sunda kuno diteliti oleh bangsa lain, seperti Perancis, Jepang, sudah tentu Belanda. Keseniannya juga disukai bangsa asing. Banyak orang asing sengaja belajar kesenian Sunda, baik di negeri kita ataupun di negaranya. [4]Konsepsi Panyca Pasagi (Sir Budi Cipta Rasa Adeg) adalah lima kekuatan dalam diri manusia (Raga Sukma Lelembutan) yang merupakan dasar kekuatan untuk menimbulkan serta menentukan Tekad Ucap Lampah Paripolah Diri manusia yang akan dan harus berinteraksi dengan Sang Pencipta, Bangsa dan Negara, Ibu Bapak Leluhur, Sesama makluk hidup, dan alam kehidupan jagar raya (Buana Pancer Sabuder Awun).
Balik ka Hyang
Naskah Kosmologi Sunda dan Jatiraga, sebagaimana ditulis oleh Undang A Darsa dan Edi S. Ekadjati (2006), pada intinya membagi jagat raya menjadi tiga, yaitu Sakala, Niskala dan Jatiniskala.Sakala atau dunia nyata dihuni oleh berbagai makhluk yang memiliki jasmani dan rohani. Mereka disebut manusia, hewan, tumbuhan, serta benda-benda lain yang da pat dilihat, bergerak dan yang diam.
Niskala atau Dunia gaib, dihuni oleh berbagai makhluk yang tak berjasad, seperti d ewa-dewi, bidadara-bidadari, apsara-apsari, ruh-ruh netral atau syanu, Bayu (Kekuatan), Sabda (Suara) dan Hedap (Itikad). Semua memiliki tugas dineraka maupun di sorga. Jati niskala, atau kemahagaiban sejati, dihuni oleh Dzat Yang Ma ha Tunggal, dinamakan pula Sang Hyang Manon, Dzat Yang Maha Pencipta disebut Si Ijunati Nistemen, pencipta batas tetapi tak terkena batas. Dunia ada dalam Dzatnya.
Munandar (2010) sama halnya dengan diatas, membagi menguraikan alam menjadi tiga. Dan menghubungkan dengan makna dari pantun Bogor, tentang perumpamaan “Pamujan batu nu tujuh, anu ngundak tilu tumpangan”, serta undakan suci yang ada dikampung Sindangbarang.
Undakan ini sama hal dengan posisi tanah di setiap kabuyutan, yang memiliki tiga undakan. Inilah penggambaran jagat raya, dimana posisi Jatiniskala dihuni oleh Sanghyang Jatiniskala, atau didalam pantun Bogor disebut :
“ Mandala Agung tea. Nya didinya ayana Sanghiyang Tunggal, anu nunggal di sakabeh Alam jeung sakabeh Jagat”. Sedangkan: “pamujaan batu nu tujuh” menggambar Guriang Tujuh, sebagai pengejawantahan dari Sanghiyang Jatniskala.Pemujaan terhadap Hyang tidak menghilangkan fungsi dari dewa-dewa lainnya, namun tetap ditempatkan di bawah Hyang. Tempat Hyang berada di Parahiyangan bukan di du nia. Parahiyangan memiliki beberapa tingkatan. Tingkat paling bawah dihuni oleh para dewa Panteon lain. Diatasnya di tempati Dewa dalam konsep Sunda, seperti Sari Dewata dan Ni Dang Larang Nawati. Di atasnya lagi dihuni oleh Dewi Sri (Pwa Sanghyang Sri), Dewi Bumi (Pwa Naga Nagini), Dewa Bulan (Pwa Naga Nagini). Posisi ini berada pada tataran alam Sakala Niskala.
Lebih jauh Munandar menjelaskan pula, bahwa tataran da lam bentuk konkrit, seperti arca batu, yantra, kitab agama, batu tertentu, ekagantra dan lain-lainnya yang sifatnya fisik, seperti yang nampak di alam manusia, berada di tataran Sakala. Inilah pembagian jagat raya dalam paradigma agama Sunda Buhun.
Konsepsi keagaamaan Sunda Buhun pada dasarnya tidak mengenal bahwa Sang Hyang tidak muncul dalam bentuk nyata, namun untuk alasan apapun agak sulit mempertegas, bahwa sanghyang dapat dikonkretkan dalam bentuk apapun, sebagaimana yang nampak nyata dialam Sakala maupun Sakala Niskala. Jika pun mungkin tentunya harus diambil dari “alam dalam wujud aslinya”.
Naskah Jatiraga menjelaskan hal ini, sebagai berikut:
“Hakekat Jatinistemen berkata, nah bayu sabda hedap, bagaimana mungkin muncul bentuk nyata, karena aku sebenarnya dalam hakikat jatinistemen; sebab aku ada lah bebasnya dari kebebasan, sebab aku adalah musta hilnya dari kemustahilan, sebab aku adalah mungkin nya dari kemungkinan, sebab aku adalah sirnanya dari kesirnaan, sebab aku adalah lepasnya dari kelepasan, sebab aku adalah aslinya dari keaslian, sebab aku ada lah jujurnya dari kejujuran ... “.
Hyang didalam naskah Kosmologi Sunda dan Jatiraga ditempatkan sebagai tujuan manusia yang paling tinggi, merupakan cita-cita jika atma (roh) manusia dikelak kemudian hari harus keluar dari kurungannya. Jatiniskala atau kemahagaiban sejati, dihuni oleh Dzat Yang Maha Tunggal, dinamakan pula Sang Hyang Manon, Dzat Yang Maha Pencipta disebut Si Iju nati Nistemen, pencipta batas tetapi tak terkena batas. Dunia ada dalam Dzatnya.
Suasana di Jatiniskala digambarkan suka tanpa mengenal duka, kenyang tanpa mengenal lapar, hidup tanpa mengenal mati, bahagia tanpa mengenal nestapa, baik tanpa mengenal buruk, pasti tanpa mengenal kebetulan, lepas tanpa mengenal ulangan hidup.
Menurut Saleh Danasasmita (1987) alam Jatiniskala, sebagai tempat :
“Suka tanpa balik duka, wareg tanpa balik lapar, hurip tanpa balik pati, sorga tanpa balik papa, hayu tanpa balik hala, nohan tanpa balik wogan, moksa tanpa balik wulan”.Kembali ke Jatiniskala adalah cita-cita orang dahulu yang saleh, sehingga kematian pun disebut ngahyang, dari ada menja di gaib, atma menuju tempat bersemayamnya Hyang. Peristiwa ngahiyang ada dua cara. Pertama, atma manusia menuju alam kalanggengan namun jasadnya masih tetap di dunia. Kedua, jiwa dan raganya lenyap, ngahiyang atau tilem. Didalam metologi urang Sunda dikenal dengan tilem, mendasarkan pada pemikiran bahwa manusia meminjam jasad dari yang berhak. Seperti jika manusia meminjam barang maka harus dikembalikan seluruhnya kepada pemiliknya, termasuk raganya. Berdasarkan mitologi pula menyatakan, bahwa ngahiyang sebagaimana yang kedua sangat jarang terjadi, kecuali jika manusia semasa hidup dapat menghindarkan semua perbuatan (tapa) yang buruk.
Teks buhun umumnya mengabarkan perihal cita-cita urang sunda buhun jika meninggalkan alam dunya, yakni balik ka Hyang lain ka Dewa. Kita harus memperteguh diri, menertibkan hasrat, ucap dan budi. Bila hal itu tidak diterapkan dan di lakukan oleh orang-orang dari golongan rendah, menengah dan tinggi semua akan dijerumuskan ke dalam neraka Si Tam bra Gohmuka. Karena ilmu manusia terungguli oleh dewata. Demikianlah kata Sanghyang Siksa.
Referensi:
[1] Ekadjati, Edi S., "Kebudayaan Sunda suatu pendekatan sejarah". Pustaka Jaya: Jakarta, 1995
[2] Monius, Anne Elizabeth. "Imagining a Place for Buddhism: Literary Culture and Religious Community in Tami-Speaking South India". Oxford University Press. 2001.
[3] Danasasmita, Danasasmita, Yoseph Iskandar, Enoch Atmadibrata]. "Rintisan penelusuran masa silam Sejarah Jawa Barat". Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1983
[4] Chaeruddin, Undang,. Drs., M.Si., "Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter". Depdiknas 2017. Basa Sunda pdf
[2] Monius, Anne Elizabeth. "Imagining a Place for Buddhism: Literary Culture and Religious Community in Tami-Speaking South India". Oxford University Press. 2001.
[3] Danasasmita, Danasasmita, Yoseph Iskandar, Enoch Atmadibrata]. "Rintisan penelusuran masa silam Sejarah Jawa Barat". Proyek Penerbitan Sejarah Jawa Barat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1983
[4] Chaeruddin, Undang,. Drs., M.Si., "Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter". Depdiknas 2017. Basa Sunda pdf
Bibliografi
- Atja, 1968, Tjarita Parahijangan: Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi. Bandung: Jajasan Kebudajaan Nusalarang.
- --------, 1970, Ratu Pakuan: tjerita Sunda-kuno dari lereng Gunung Tjikuraj. Bandung: Lembaga Bahasa dan Sedjarah.
- Darsa, Undang A. dan Edi S. Ekadjati, 2006, Gambaran Kosmologi Sunda (Kropak 420) Silsilah Prabu Siliwangi, Mantera Aji Cakra, Mantera Darma Pamulih, Ajaran Islam (Kropak 421), Jatiraga (Kropak 422); Studi Pendahuluan, Transliterasi, Rekonstruksi, Suntingan, dan Terjemahan Teks. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Ekadjati, Edi S., 1988, Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran dengan The Toyota Foundation.
- Ekadjati, Edi S. dan Undang A. Darsa, 1999, Jawa Barat: Koleksi Lima Lembaga. Katalog induk naskah-naskah Nusantara Jilid 5. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise d’Extreme Orient.
- Ekadjati, Edi S, 2001, ‘Naskah Sunda: Sumber Pengetahuan Budaya Sunda’. Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) Jilid I. Diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Rancagé bekerjasama dengan Kiblat Buku Utama. Cetakan pertama (2006).
- Danasasmita, Saleh et.al., 1986, Kropak 408 (Sewaka Darma) dan Kropak 630 (Sanghyang Siksakandang Karesian): Transkripsi dan Terjemahan. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Direktorat Jendral Kebudayaan Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Danasasmita, Saleh et.al., 1987, Sewaka Darma (Kropak 408), Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630), Amanat Galunggung (Kropak 632): Transkripsi dan Terjemahan”. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jendral Kebudayaan Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Darsa, Undang A., 1998, Sanghyang Hayu: Kajian Filologi Naskah Bahasa Jawa Kuno di Sunda pada Abad XVI. Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Darsa, Undang A., Edi S Ekadjati, Mamat Ruhimat, 2004, Darmajati (naskah lontar kropak 423): Transliterasi, Rekonstruksi, Suntingan, dan Terjemahan Teks. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Noorduyn, J. dan A. Teeuw, 2006, Three old Sundanese poems. Leiden: KITLV Press.
- Pleyte, C.M., 1913, ‘De Patapaan Adjar Soeka Resi: ander gezegd de kluizenarij op den Goenoeng Padang: Tweede bijdrage tot de kennis van het oude Soenda’. TBG LV: 321-428.
- --------, 1914a, (met medewerking van Raden Ngabei Poerbatjaraka), ‘Een pseudo-Padjadjaransche kroniek; Derde bijdrage tot de kennis van het oude Soenda’, Tijdschrift voor Indische Taal, Land-en Volkenkunde (TBG) 56:257-80.
- --------, 1914b, ‘Poernawidjaja’s Hellevaart of de Volledige Verlossing. Vierde bijdrage tot de kennis van het oude Soenda.’ Tijdschrift voor Indische Taal, Land-en Volkenkunde (TBG) 16:450-70.
- Ayatrohaédi, 1988, Serat Dewabuda; Laporan Penelitian. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ayatrohaédi dan Munawar Holil, 1995, Kawih Paningkes; Alihaksara dan Terjemahan Naskah K. 419 Khasanah Perpustakaan Nasional Jakarta. Laporan Penelitian Fakultas Sastra Universitas Indonesia.