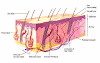|
| Foto:banten.co |
Sebagai suatu bentuk persekutuan hidup, orang-orang Kanekes dalam yang tinggal bersama di daerah sebelah dalam desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak provinsi Banten sebelah selatan merupakan rumpun dari kebudayaan Sunda; dalam terminologi antropologi untuk persekutuan hidup seperti orang-orang Baduy itu sebenarnya lebih tepat disebut komunitas daripada masyarakat (Koentjaraningrat, 1990: 61); hanya untuk lebih memudahkan pemahaman maka istilah yang akan dipakai untuk menamakan persekutuan hidup tersebut dalam tulisan ini adalah – ‘orang Kanekes’.
Hal tentang penamaan persekutuan hidup, Baduy, sebenarnya hanya berlaku pada fihak diluar persekutuan itu, masyarakat suku Baduy itu sendiri sebenarnya tidak suka menamakannya demikian, tetapi lebih menyatakan diri sebagai orang ‘Kanekes’. Istilah Baduy menurut mereka adalah berkonotasi kurang baik karena berkenaan dengan kelompok Badwi, satu kelompok pengembara padang pasir di tanah Arab yang dipandang rendah peradabannya (Ekajati, 1995: 54). Kemungkinan sebutan Baduy yang mempunyai konotasi ejekan berasal dari masyarakat sekitarnya yang telah memeluk agama Islam.
kehidupan orang Kanekes yang ‘terisolir’ selama berabad-abad hingga sekarang, sikap hidup mereka selalu cenderung menolak masuknya kebudayaan luar dan mempertahankan cara hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur mereka, dimana mereka masih banyak menyimpan unsur, pola, dan sistem masyarakat dan kebudayaan Sunda lama. Sebenarnya istilah terisolir (terasing) dalam kasus orang Kanekes adalah relatif karena hubungan dengan masyarakat luar ternyata berlangsung secara terbuka, baik intensitas kunjungan orang Kanekes keluar dari desanya maupun intensitas kunjungan studi bahkan wisata banyak orang ke desa Kanekes. Istilah keterasingan disini bisa diartikan sebagai pengasingan diri.
Lokasi pemukiman yang terpencil, sikap hidup yang kukuh mempertahankan adat istiadat dari leluhur, sikap keras menolak pengaruh kebudayaan luar, serta cara hidup yang mandiri bila dibandingkan dengan beberapa bentuk masyarakat terasing lainnya yang ada di Indonesia, rupanya keadaan inilah yang menjadi ciri pembeda dan menonjol dari orang Kanekes.
Berdasarkan pada tingkat adatnya, orang Kanekes dapat diklasifikasikan atas dua kelompok sosial, yaitu orang Kanekes Dalam (Baduy dalam) dan orang kanekes Luar (Baduy luar); orang Kanekes dalam tinggal di tiga kampung terpisah yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik, sedangkan orang Kanekes luar adalah orang Kanekes yang bermukim di banyak kampung di luar kampung Kanekes dalam.
Keajegan orang Baduy dalam mempertahankan kepercayaan, tradisi, serta kecenderungan untuk menolak perubahan baik yang berasal dari dalam dan luar masyarakat ternyata terkait dengan berbagai sektor kehidupan; adalah cukup menarik melihat keterkaitan itu dengan konsep ruang yang ternyata merupakan fenomena penting dalam kepercayaan dan falsafah hidup orang kanekes menurut dimensi makro dan mikro kosmos yang terwujud dalam tiga alam yaitu Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hiyang Keresa, yang letaknya di alam atas, Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan mahluk lainnya, yang letaknya di alam tengah, serta Buana larang, yaitu neraka, yang letaknya di alam bawah.
Konsep Ruang Tempat Tinggal pada Masyarakat Sunda
Dalam satu tulisan, Garna (1980) mengemukakan bahwa pada kehidupan masyarakat Sunda yang tinggal di pedesaan, terdapat hubungan yang erat antara sistem matapencaharian hidup mereka dengan bentuk desa, atau sekurangnya warga masyarakat desa tersebut berusaha agar tempat kegiatan matapencaharian itu dekat, disekitarnya atau berada di tempat mereka itu sendiri bertempat tinggal (Garna, 1980: 228). Rumah dan sekelilingnya berupa pekarangan, pagar, dan bangunan lain seperti lubung padi dan balai pertemuan (bale) adalah kesatuan kecil yang membentuk pemukiman tempat tinggal warga masyarakat dan mengembangkan kemampuan manusiawinya.Kumpulan beberapa rumah yang kadang-kadang terdiri dari 4 – 5 rumah yang membentuk satu kesatuan yang lebih besar dari rumah dan sekelilingnya sebagai unit terkecil yang disebut babakan. Bentuk yang lebih besar dari babakan yang terdiri dari beberapa puluh rumah dengan berbagai sarana dan prasarana kehidupan lainnya, seperti balai pertemuan, lubung padi, tempat mandi umum, lapangan, areal pekuburan, jalan-jalan setapak, kebun atau sawah membentuk satu persekutuan yang bias di sebut sebagai kampung; dan bentuk persekutuan yang lebih besar dari kampung disebut sebagai desa. Pada dasarnya, satu desa itu terdiri dari beberapa kampung, namun tidak selalu satu kampung itu terdiri dari beberapa babakan.
Untuk beberapa kampung atau desa pada masyarakat Sunda biasanya mengambil nama dari sumber air, sungai atau gunung yang dihubungakan dengan peristiwa yang terjadi di sana; sebutan awal Ci (asal kata Sunda cai yang berarti air) adalah sangat umum dipakai sebagai nama suatu daerah. Orang Kanekes bagian dalam atau menurut istilah setempat disebut sebagai Urang Tangtu yang bertempat tinggal di daerah pedalaman desa Kenekes, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten bagian selatan mencirikan keterhubungan nama daerah mereka dengan air ini, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik.
Tempat, Kesejarahan, dan Kepercayaan Orang Kanekes
Desa Kanekes sebagai tempat bermukin orang kanekes terletak di bagian selatan daerah kecamatan Leuwidamar yang merupakan daerah aliran sungai Ciujung pada bagian utara pegunungan Kendeng, termasuk wilayah Banten selatan. Daerah desa Kanekes ini terdiri atas hutan, lading, semak belukar, dan perkampungan. Pemukiman orang Kanekes merupakan daerah berbukit yang makin ke arah selatan makin curam lereng-lerengnya; hutan yang lebat di sekitar pegunungan Kendeng merupakan sumber air yang penting bagi daerah aliran sungai Ciujung di sebelah utara Banten. Orang Kanekes berkumpul dalam satu kesatuan pemukiman yang disebut babakan atau kampung.Menurut kesejarahannya, orang Kanekes merupakan bagian dari suku bangsa Sunda, selain dari cirri-ciri fisik yang tidak berbeda dengan orang-orang Sunda lainnya juga dari segi kebahasaan sama-sama merujuk pada satu rumpun bahasa yang sama, bahasa orang Kanekes adalah bahasa Sunda. Dalam satu analisa sejarah, diperkirakan mereka pindah di daerah terpencil pegunungan Kendeng ini pada abad ke 16, yaitu bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Padjadjaran. Dahulu, sebelum Islam masuk ke Indonesia dan Jawa, pengaruh agama Hindu dan Budha sangat kuat, termasuk kerajaan Padjadjaran. Pada tahun 1579 masuklah Islam untuk menghancurkan Padjadjaran dan masyarakat disana berpindah ke agama Islam. Ada sekelompok masyarakat yang menolak untuk masuk Islam, kemudian mereka berpindah tempat dan mengasingkan diri; kelompok tersebut kemudian dinamakan dengan suku Baduy.
Berbagai penelitian yang kemudian dilakukan tentang keberadaan masyarakat suku Baduy ini menghasilkan pendapat yang berlainan dengan analisa kesejaran di atas; seperti yang diteliti oleh Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda (1986) bahwa bila berbicara mengenai asal usul masyarakat Kanekes hendaklah bertitik tolak dari kedudukan masyarakat tersebut dalam konteks masyarakat Sunda lama. Masyarakat Kanekes mempunyai kedudukan dan tugas khusus dalam hubungan dengan masyarakat Sunda secara keseluruhan. Dalam hal ini, masyarakat Kanekes secara turun temurun berkedudukan sebagai mandala dan semua warga masyarakatnya mengemban tugas untuk melakukan tapa (bekerja-beraktifitas) di mandala. Sedangkan masyarakat Sunda lainnya, di luar masyarakat mandala, berkedudukan sebagai nagara dan semua warga masyarakatnya mengemban tugas untuk melakukan tapa di nagara (Danasamita & Djatisunda, 1986: 3).
Mandala adalah satu konsep dalam kerajaan Sunda lama yang berarti tempat suci untuk pusat kegiatan keagamaan; di mandala ini hidup kelompok masyarakat (pendeta, murid-murid, atau bahkan pengikut mereka) yang membaktikan seluruh hidupnya bagi kepentingan kehidupan beragama. Berdasarkan prasasti Banten dan naskah Sunda kuno, diketahui bahwa dalam masyarakat Sunda lama mandala itu disebut pula dengan istilah kabuyutan, yang terdiri dari dua jenis: (1) Lemah Dewasasana dan (2) Lemah Parahiyangan. Lemah Dewasasana adalah mandala sebagai tempat untuk pemujaan dewa, kegiatan ini berlaku bagi penganut agama Hindu atau Budha, dan Lemah Parahiyangan, disebut juga sebagai kabuyutan jatisunda, adalah mandala sebagai tempat untuk pemujaan hiyang, kegiatan mana berlaku bagi penganut yang memuja terhadap arwah leluhur atau nenek moyang yang berlaku sejak jaman prasejarah. Dari prasasti dan naskah-naskah Sunda kuno itu dapat diketahui beberapa buah mandala di tanah Sunda dimana salah satunya adalah Kanekes, Denuh (Kropak, Carita Parahiyangan).
Sesuai dengan isi kepercayaan orang Kanekes yang dinamai mereka sendiri sebagai agama Sunda Wiwitan dan nama lain lokasi pemukiman mereka serta nama sebuah sungai di situ, yaitu Lebak Parahiang dan Ciparahiyangan, maka Kanekes kiranya sebuah mandala yang tergolong lemah parahiyangan. Berdasarkan pengakuan masyarakat Kanekes sendiri, dikatakannya bahwa sejak semula leluhur kereka hidup di daerah yang mereka duduki sekarang, yaitu desa Kanekes; leluhur mereka bukan berasal dari mana-mana dan buka pula berasal sebagai pengungsi. Bila dihubungkan dengan asal usul mereka dengan kaum pelarian dari Pakuan Padjadjaran bahkan mereka bersikukuh bahwa sejak zaman Nabi Adam AS pun leluhur mereka telah bermukim di daerah Kanekes (Ekajati, 1995: 62-64).
Sesuai dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan orang Kanekes, agaknya sulit untuk menentukan termasuk kelompok agama besar apa yang dianut mereka; walaupun ada beberapa pengaruh dari agama Hindu seperti tergambarkan dalam nama-nama batara, juga pengaruh agama Islam seperti dalam istilah Syahadat (Suhamihardja, 1980: 281), namun dalam kenyataannya praktika ritual mereka lebih menujukkan pada bentuk Animisme, yaitu bentuk kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Orang Kanekes menyebut agamanya sebagai Sunda Wiwitan, yang berarti mula-pertama, asal, pokok, atau jati; dalam hal ini agama yang dianut orang Kanekes adalah agama Sunda asli, yang menurut Carita Parahiyangan adalah agama Jatisunda.
Dalam mitologi orang Kanekes, kekuasaan tertinggi berada pada apa yang disebut Sang Hiyang Keresa (Yang Mahakuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki) atau Batara Seda Niskala (Yang Gaib) dimana semua dewa dalam konsep agama Hindu (Brahma, Wisynu, Syiwa, Indra, Yama, dan lain-lain) tunduk pada Batara Seda Niskala ini – semuanya bersemayam di Buana Nyungcung, merupakan tempat tertinggi dalam tiga klasifikasi kosmologi orang Kanekes. Tempat manusia dan mahluk lain hidup di dunia disebut sebagai Buana Panca Tengah. Sedangkan tempat atau alam bawah, yaitu neraka, disebut Buana Larang.
Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapisan alam yang tersusun dari atas ke bawah; lapisan teratas disebut Bumi Suci Alam Padang atau menurut kropak 630 bernama alam Kahiyangan atau mandala Hiyang, lapisan ini merupakan tempat tinggal Nyi Pohaci Sanghiyang Asri dan Sunan Ambu. Sanghiyang Keresa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana, salah satu batara itu bernama Batara Cikal, berusia paling tua, dianggap sebagai leluhur orang Kanekes.
Dalam kepercayaan orang Kanekes, tanah atau daerah di dunia ini (Buana Panca Tengah) dibedakan berdasarkan tingkatan kesuciannya. Sasaka Pusaka Buana dianggap sebagai tempat yang paling suci, hampir berdampingan dengan Sasaka Domas. Selanjutnya, berurutan tingkat kesuciannya makin menurun adalah kampung dalam, kampung luar (panamping), Banten, Tanah Sunda, dan luar Sunda.
Ada dua tempat yang dianggap sangat suci di kalangan orang kanekes, dan tidak sembarang orang, apalagi orang luar Kanekes, bisa ke tempat ini – hanya ketua adat tertinggi (pu-un) saja beserta orang-orang kepercayaannya yang dapat melakukan upacara ritual disana. Tempat pertama disebut dengan Sasaka Pusaka Buana atau disebut juga Pada Ageung dan Arca Domas, merupakan tempat yang paling suci yang dianggap sebagai titik awal terbentuknya dunia dimana ke 7 batara diturunkan. Letaknya di bukit Pamutuan, daerah hulu sungai Ciujung disebelah ujung barat pegunungan Kendeng. Tanggung jawab pemeliharaan Sasaka ini berada pada tangan pu-un Cikeusik, dan hanya pu-un Cikeusik dengan beberapa orang kepercayaannya saja yang mengetahui tepatnya lokasi itu berada. Tempat suci kedua yaitu Sasaka Domas atau Mandala Parahiyangan, lokasinya di hulu sungai Ciparahiyangan, termasuk kompleks hutan larangan. Tanggungjawab pemeliharaannya berada di tangan pu-un Cibeo.
Ruang Dalam Konsep Kedudukan Dan Kewajiban
Dalam masyarakat desa Kanekes terdapat satu bentuk stratifikasi sosial yang didasarkan kepada pembagian wilayah sesuai dengan status kemandalaan Kanekes. Dalam hal ini, wilayah Kanekes dibagi atas 3 wilayah berdasarkan tingkat kemandalaannya, yaitu (1) wilayah Tangtu, yang terletak paling jauh dari masyarakat luar dan memiliki kadar kemandalaan yang terbesar dan sepenuhnya sebagai mandala; (2) wilayah Panamping, terletak di luar wilayah Tangtu yang memiliki tingkat kemandalaan lebih kecil, (3) wilayah Dangka, terletak diluar wilayah Panamping dengan tingkat kemandalaan lebih kecil lagi. Seiring dengan tingkat kemandalaan ini, tuntutan kehidupannya pun berbeda pula; penduduk wilayah Tangtu dituntut secara penuh untuk hidup sesuai dengan aturan kemandalaan, sedangkan tuntutan penduduk di wilayah Panamping dan Dangka akan lebih longgar dari itu. Stratifikasi sosial orang kanekes ini sejajar dengan tingkat dan kadar kemandalaan, semakin tinggi tingkat dan kadar kemandalaannya, makin tinggi pula tingkat sosialnya; semakin rendah tingkat dan kadar kemandalaannya, makin rendah [pula tingkat sosialnya. Masyarakat Tangtu terbagi lagi menjadi 3 kelompok sosial berdasarkan kampung tempat tinggalnya dengan merujuk pada konsep Telu Tangtu (kropak 630 : Tri Tangtu); suatu konsep yang hidup dalam kerajaan Sunda kuno yang melibatkan satu kesatuan antara tiga unsur peneguh dunia dan dilambangkan dengan raja sebagai sumber wibawa, rama sebagai sumber ucap (yang benar), dan resi sebagai sumber tekad (yang baik); dunia bimbingan berada ditangasn sang rama, dunia kesejahteraan berada ditangan sang resi, dan dunia pemerintahan berada ditangan sang raja (Atja & Saleh Danasasmita, 1981: 30, 37). Pertama, kelompok masyarakat yang menetap di kampung Cibeo, disebut sebagai Tangtu Parahiyangan yang mempunyai tugas sebagai ‘Sang Prabu’; kedua, kelompok masyarakat yang menetap di kampung Cikartawana, disebut sebagai Tangtu Kadu Kujang yang mempunyai tugas sebagai ‘Sang Resi’; ketiga, kelompok masyarakat yang menetap di kampung Cikeusik, disebut sebagai Tangtu Pada Ageung yang mempunyai tugas sebagai ‘Sang Rama’.Penggunaan Ruang dalam masyarakat Tangtu
Berdasarkan pola pengelolaan tata ruangnya, kawasan Tangtu secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu zona bawah sebagai tempat pemukiman, zona tengah sebagai tempat bercocok tanam, serta zona atas yang merupakan hutan tua yang diperuntukan sebagai tempat untuk praktek pemujaan.Zona pertama, yaitu areal di sekitar daerah lembah yang dekat dengan sumber-sumber air baik dari sungai maupun sumber air tanah. Areal ini digunakan sebagai tempat pusat aktivitas keseharian penduduk, yang meliputi tempat permukiman yang terdiri dari rumah-rumah tradisional penduduk biasa, rumah ‘pu-un’, balai pertemuan (bale kapu-unan), penumbukan padi /’saung lisung’, lapangan, tempat penyimpanan padi penduduk atau ‘leuit’, sumber-sumber air minum, tempat mandi – cuci – kakus, dan tempat pekuburan penduduk (Garna, 1980: 236-238).
Di sekitar pemukinan ini, biasa ditumbuhi aneka ragam tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan, yang tumbuh liar, setengnah liar, atau masih liar. Hutan antropogenik di daerah kampung penduduk yang rimbun menyerupai struktur vegetasi hutan alam, biasanya disebut sebagai ‘dukuh lembur’ atau ‘leuweung lembur’. di daerah dukuh lembur tersebut, di bawah pepohonan rindang, ditempatkan lumbung padi (leuit). Menurut ‘pikukuh’ orang Kanekes, dukuh lembur tidak boleh dirusak atau ditebangi karena dianggap sebagai perlindungan kampung dan sekaligus menghasilkan aneka ragam buah-buahan untuk kepentingan sosial ekonomi penduduk (Iskandar, 2006).
Di sekitar pinggiran rumah penduduk yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kayu dan rumpun bambu, banyak ditemukan mata air (Kanekes: cai nyusu) dan di beberapa tempat itu kemudian dibuat semacam pancuran yang dimanfaatkan untuk mandi, sekedar mencuci, dan dipergunakan untuk air minum (Iskandar, 2006). Sungai dan beberapa anak sungai lainnya juga dipakai sebagai tempat untuk mandi, mencuci dan buang air, selain juga merupakan tempat untuk menangkap ikan pada waktu-waktu tertentu. Zona kedua, yaitu areal di bagian luar pemukiman penduduk di atas lembah-lembah bukit yang terdiri dari hutan sekunder atau hutan produksi yang dibersihkan dan dipergunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam tadah hujan dengan pola peladangan berpindah (slash and burn agriculture).
Zona ketiga, berupa areal di puncak bukit yang diperuntukan sebagai tempat yang dianggap suci (sakral) berupa hutan tua dan terlarang untuk diberdayakan guna kehidupan praktis penduduk. Hutan ini disebut oleh masyarakat setempat sebagai hutan titipan (‘leuweung titipan’) atau hutan tua (‘leuweung kolot’) yang diperuntukan sebagai tempat untuk melakukan upacara keagamaan. Terdapat dua tempat yang dianggap suci oleh penduduk Kanekes, yang pertama adalah kawasan hutan Sasaka Pusaka Buana atau Pada Ageung dikawasan hulu sungai ciujung, yaitu di sebelah selatan Kampung Cikeusik; dan yang kedua yaitu hutan Sasaka Domas di kawasan hulu sungai Ciparahiang, anak sungai Ciujung di sebelah selatan kampung Cibeo.
Penataan dan fungsi ruang dalam rumah
Dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, komunitas Kanekes Tangtu mewujudkannnya dalam bentuk yang sangat sederhana. Mereka hanya membangun tempat tinggal seperlunya dengan arsitektur bangunan yang sama; setiap rumah dirancang untuk tidak langsung berhubungan dengan tanah tetapi berbentuk panggung dengan penyangga dari batu setinggi kurang lebih 75 cm. Material bangunan untuk rumah sendiri sangat sederhana yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan setempat mencakup kayu-kayu ringan, bambu baik yang utuh, dibelah (palupuh), atau dianyam (bilik) dan serat pohon enau (injuk), semacam daun pandan, daun kelapa, atau alang-alang kering sebagai bahan untuk atap rumah.Untuk satu Keluarga inti, hanya ada 2 – 3 ruangan di dalam rumah, yaitu 1 ruangan agak besar untuk tempat berkumpul keluarga, tidur anak laki-laki, tempat menerima tamu, tempat menyimpan berbagai perkakas rumah tangga, dan tempat memasak/perapian yang merangkap tempat untuk makan; 1 ruangan untuk orang tua, dan 1 ruangan lagi untuk anak perempuan. Dengan konstruksi rumah panggung seperti di atas, maka ada ruang kosong di bawah rumah yang biasanya difungsikan sebagai tempat untuk memelihara ternak.
Rumah pimpinan komunitas (puun) dipisahkan dengan tempat pemukiman penduduk biasa yang dibatasi oleh satu lapangan dimana tidak sembarang orang bias memasuki areal ini karena sangat terlarang menurut kepercayaan setempat. Kesucian tanah, apalagi rumah kepala adat, sesuai dengan kehendak nenek moyang mereka (‘karuhun’), haruslah dipelihara dari sentuhan orang yang bukan warga Baduy dengan cara tidak menginjak dan berada di tanah dan rumah ini.
Jarak antara rumah berdekatan, pekarangan depan rumah dan belakang agak lebih luas dibandingkan dengan pekarangan di kedua sampingnya yang agak sempit. Jarak yang dekat ini memudahkan wanita-wanita meminta api dari tetangganya untuk keperluan dapur (hawu). Hubungan dekat terjalin dengan erat, tidak saja dengan saling berkunjung, tetapi terjadi pula pada waktu mereka sama-sama pergi ke sungai atau pancuran, dan sampil menumbuk padi di saung lisung. Sumber air dan saung lisung ini mempunyai fungsi ganda; disini wanita-wanita bias saling bertemu, berbicara, dan mengobrol untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan hidup (terutama dalam hal memelihara dan mengasuh anak, relasi antara angota keluarga dan hal-hal kewanitaan lainnya yang seringkali disampaikan secara terbuka dan berkelakar).
Orang Tangtu yang matapencahariannya berladang ternyata memiliki dua pola tempat tinggal, pertama adalah tempat tinggal yang tetap berupa kampung serta tempat tinggal di ladang (saung huma atau dangau ladang) untuk waktu-waktu tertentu, biasanya pada saat-saat pertama menanam dan saat-saat menjelang akan panen, yang serupa dengan tempat tinggalnya di kampung; hanya saja pola mukimnya tidak terpusat seperti di kampung tetapi tersebar di ladang masing-masing.
Lingkungan Matapencaharian Hidup Sistem perekonomian orang Kanekes Tangtu cenderung menggambarkan sistem yang tertutup, dalam arti aktivitas perekonomiannya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diproduksi serta dikonsumsi di lingkungan mereka sendiri. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi utama dan penting, dengan pandangan mereka bahwa aktivitas ekonomi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk memperkaya diri, maka tidak banyak aktivitas jenis ekonomi yang dilakukan mereka seperti masyarakat modern pada umumnya.
Seluruh warga komunitas belajar untuk bekerja di sektor pertanian sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, mereka dituntut untuk melakukan terhadap apa yang telah digariskan apakah tentang waktu pengolahan tanah, jenis tanaman, proses pengolahan tanah, maupun memanen hasil pertaniannya. Pada masa tidak sedang bekerja di ladang, para laki-laki bekerja di hutan untuk berburu dan memanen madu, sementara perempuan bekerja menenun dirumah untuk membuat baju, selendang, sarung, serta kerajinan rumah tangga lainnya. Hasil dari aktivitas ekonomi ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk upacara-upacara, sedangkan sisanya mereka jual ke daerah luar untuk ditukar dengan kebutuhan yang tidak mereka hasilkan seperti garam, minyak goreng, serta bumbu-bumbu.
Orang Kanekes dalam dipebolehkan untuk berburu namun hanya dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara tertentu saja; hewan-hewan buruan juga terbatas pada jenis kancil, menjangan, dan tupai.
Sistem Perladangan
Sistem pertanian di Indonesia maupun di beberapa Negara pertanian di dunia sudah sangat jarang sekali menggunakan sistem berladang, karena dengan tingkat pertambahan penduduk yang semakin banyak maka pemberdayaan lahan menjadi semakin tidak efektif dan cenderung tidak ramah lingkungan. Menurut orang Kanekes, sistem berladang yang mereka kerjakan sesuai dengan kepercayaan serta pandangan hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan secara besar-besaran pada alam, karena justru dengan demikian akan menimbulkan ketidakseimbangan alam dalam konteks mirko dan makro kosmos (Boolars, 1984: 33).Dengan sistem berladang, mereka tidak malakukan perubahan bentuk alam karena mereka menanam mengikuti alam yang ada, mereka menanam padi dan tumbuhan lainnya sesuai dengan lereng disana, dan tidak membuat terasering. Sistem pengairannya tidak menggunakan irigasi teknis, tetapi hanya memanfaatkan hujan yang ada. Ada pelarangan penggunaan air sungai dan sumber mata air lainnya untuk mengairi sawah atau ladang, hidup kepercayaan di lingkungan mereka bahwa dengan membelokkan arah aliran air sungai maupun mata air untuk pertanian akan merubah bentuk alam dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan alam sehingga akan ada kerusakan alam.
Pemupukan serta perawatan pertanian dilakukan semuanya adalah organik, tidak ada unsur kimia yang digunakan dalam mengelola pertanian. Lahan untuk berladang dipilih yang memiliki humus banyak hal mana biasanya ditandai dengan banyaknya daun-daun yang berserakan di ladang tersebut. Semakin lama lahan tersebut tidak digunakan sebagai ladang, maka akan semakin banyak humus di daerah tersebut dan semakin subur.
Hasil panen padi disimpan di lubung bersama yang berada di tepi kampung, selain untuk menyimpan padi untuk persediaan selama satu tahun, lumbung juga digunakan untuk menyimpan bibit-bibit unggul untuk ditanam pada tahun berikutnya. Lumbung ditutup rapat untuk mencegah padi dari hama maupun hewan lainnya. Lumbung padi tidak bisa di buka sembarang waktu, tetapi harus dengan seizin pemuka masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan itu. Kebutuhan padi untuk hidup sehari-hari, maupun untuk upacara-upacara telah direncanakan bersama sehingga tidak ada keluarga yang kekurangan maupun kelebihan persediaan padi di rumah.
Dalam hal penggunaan lahan pertanian juga rumah tempat tinggal, komunitas Kanekes tidak mengenal konsep kepemilikan individual, semuanya adalah milik kelompok (persekutuan – komunal), lahan disana merupakan tanah adat yang digunakan secara bersama-sama, dan tentu saja melalui proses pengaturan. Di wilayah Kanekes dalam ini tidak berlaku sistem jual beli maupun sewa menyewa lahan, yang ada adalah kepemilikan tanaman. Tanaman menjadi milik orang yang menanam sementara lahan tetap menjadi milik adat; dengan system ini, adat dapat mengendalikan lahan dan peruntukannya. Lahan-lahan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian digunakan secara bergiliran oleh keluarga-keluarga disana.
Pandangan Lingkungan Alam, Sosial budaya, dan transendental
Kondisi lingkungan di kampung-kampung Kanekes dalam memiliki kualitas yang baik yang ditandai dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang masih tinggi. Banyak jenis-jenis flora dan dauna yang ada di Kanekes tetapi tidak ditemukan di wilayah lainnya. Beberapa satwa yang hidup di sana tergolong liar dan langka sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Kemandirian hidup mereka menciptakan iinteraksi masyarakat dan lingkungan yang sangat erat dan saling tergantung.Tempat tinggal yang relatif jauh dari peradaban modern dan kehidupan yang tradisional yang tetap dipertahankan oleh komunitas Kanekes menyebabkan mereka memiliki sifat-sifat yang khas. Cara hidup tradisional yang sarat dengan nilai-nilai toleransi antara lingkungan sosial-budaya, alam, dan transendental dalam kehidupan masyarakat Baduy sebenarnya adalah konsep yang sangat modern; orientasi pada masa yang akan datang seperti terwujud dalam mekanisme pengelolaan lubung padi adalah salah satu kriteria modern yang dikemukakan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck (1961) atau oleh Inkeles (1994); Kerusakan lingkungan sebagai salah satu indikator dari masyarakat pembangun seperti yang dikemukakan oleh Budiman (1995: 6) juga diterjemahkan dengan baik oleh komunitas ini dalam penataan lingkungannya. Proteksi terhadap lingkungannya ini ditujukan untuk mempertahankan kehidupan mereka agar supaya tetap utuh dan bisa memenuhi kebutuhann hidup sendiri.
Pandangan mereka dalam kelestarian lingkungan, sama dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan dimana mereka beranggapan bahwa kerusakan lingkungan atau perubahan terhadap bentuk limngkungan akan mengancam sumber kehidupan mereka yang berakibat dengan kelaparan dan kekurangan secara ekonomi lainnya. Kehancuran kehidupan akibat kerusakan lingkungan akan memicu kepunahan orang Kanekes, oleh sebab itu mereka melarang bahkan melawan fihak luar yang berusaha untuk mengadakan berubahan disana, termasuk pemerintah.
Prinsip dan falsafah kehidupan di Kanekes merupakan instrumen utama bagi pengelolaan lingkungan disana, mereka menganggap dirinya termasuk dalam dimensi lingkungan secara totalitas; Petuah sekaligus amanat dari nenek moyangnya, yang dianggap sebagai bagian dari unsur kepercayaan, mengisyaratkan bahwa mereka adalah kaum yang dipilih sebagai penjaga alam desa Kanekes khususnya yang merupakan salah satu pusat alam, petuah dan amanat mana sedemikian kuat terinternalisasi dalam hati dan pikiran segenap orang Kanekes yang berpengaruh positif terhadap segala tindakannya kemudian. Keyakinan kuat dari orang Kanekes dalam menjaga lingkungan dari kerusakan didukung oleh keyakinan mereka bahwa Kenekes merupakan wilayah pusat tanah Jawa (Prihartoro, 2006: 17; Ekajati, 1995: 70). Mereka berkeyakinan jika pusat dari alam mengalami kerusakan maka akan menimbulkan bencana alam di tempat lainnya. Untuk menghindari dari kerusakan atau bencana alam di tempat lain itu, maka komunitas Kanekes terutama pemimpin mereka harus sangat disiplin menjaga kelestarian lingkungan.
Aturan untuk menghindari perubahan terhadap bentuk alam dalam segala aspek kehidupan merupakan bentuk untuk menjaga kelestarian alam antar generasi. Struktur pemerintahan dan adat yang dikombinasikan untuk menjaga eksistensi hukum adat dan tetap menjadi bagian dari lingkungan luar. Prinsip ekonomi yang diterapkan juga menjadi kunci keberlangsungan komunitas Kanekes, yaitu bahwa segenap aktivitas ditujukan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang merupakan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan diluar primer dianggap sebagai pemenuhan nafsu atau keinginan saja yang akan memicu eksploitasi sumber daya alam dan kesenjangan sosial.
Refrensi
- Boelaars, Y.(1984). Kepribadian Indonesia Modern. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiman, Arif. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danasasmita, Saleh-Djatisunda, Anis. (1986). Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud.
- Ekajati, Edi S. (1995). Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Garna, Yudistira. (1980). Pola Kampung dan Desa, Bentuk Serta Organisasi Rumah Masyarakat Sunda; dalam Edi S. Ekajati: Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya :. Jakarta : PT Giri Mukti.
- Inkeles, Alex. (1994). Modernisasi Manusia; dalam Myron Weiner : Modernisasi Dinamika Pertubuhan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kluckhohn, C–Strodtbeck, FL. (1961).Variations of Value Orientation; dalam Koentjaraningrat: Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1990). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Peursen, Van.CA. (1976). Strategi Kebudayaan. Jakarta-Yogyakarta : PT Gunung Mulia-Kanisius.
- Suhamihardja, Suhandi A. (1980). Agama, Kepercayaan dan Sistem Pengetahuan; dalam Edi S. Ekajati: Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya . Jakarta : PT Giri Mukti Laporan, Artikel, Surat Kabar : Asia GOOD ESD Practice Project.
- Prihartoro, Feri. (2006). Sustainable Life of BADUY Tribe Community. BINTARI (Bina Karya Lestari Foundation). Harian Surat Kabar Kompas.
- Iskandar Johan. (2006). Baduy, Urang Gunung yang Cinta Air.