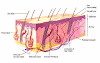|
| Prasasti Tembaga Kebantenan |
Istilah sastra ditemukan juga pada naskah Sanghyang Sasana Maha Guru (disingkat SSMG), koropak 621 koleksi Perpustakaan Nasional RI (PNRI). Berdasarkan catatan kepurbakalaan N.J. Krom (1914), naskah ini termasuk dalam koleksi kropak Bandung yang diakuisisi oleh Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen (BGKW) dari kolektor R.A.A. Martanagara (Bupati Bandung, 1893-1918).
 |
| Naskah Sanghyang Sasana Maha Guru |
Teks SSMG sekarang disimpan dalam peti no. 15, ditulis dalam 36 lempir daun lontar, ukurannya 34, 3 cm x 4 cm., 4 baris tiap lempir. Aksaranya Sunda Kuna, bahasanya Sunda Kuna dan Jawa Kuna, bentuknya prosa. Sekalipun ada dua lempir yang sudah patah, tetapi secara umum keadaannya terbilah baik.
Teks SSMG pernah diteliti oleh Pleyte tahun 1914, sekalipn baru secara fragmentaris, dijadikan lampiran untuk melengkapi artikelnya yang berjudul ‘Poernawidjaja’s hellevaart, of de Volledige verlossing; Vierde bijdrage tot de kennis van het oude Soenda’ (1914). Pleyte memberikan judul naskah sebagai "Sanghyang Pustaka."
Dasa Wredi
Konsep Dasa Wredi terdapat dalam bab ke-3, lempir ke-6 s.d ke-7. Eusina menjelaskan konsep sastra sebagai tulisan. Sacara etimologis, Dasa Wredi terbentuk dari dua kata: dasa ‘sepuluh’ dan wredi (skt. wrddhi) ‘kamajuan’. Singkatnya, dasa wredi adalah sepuluh tanda kemajuan. Yang jadi cirinya, yaitu adanya tulisan. Tulisan yang ditulis dalam sapuluh jenis media: emas, perak, tembaga, baja, besi, batu, kayu, pejwa (bambu), taal (lontar), dan gebang (nipah).Tulisan di atas emas diketemukan di candi Batujaya, Karawang, berupa lambaran prasasti Buddha yang menggunakeun aksara Pasca-Palawa. Tulisan di atas perak belum pernah diketemukan. Tulisan di atas tembaga artefaknya yaitu prasasti Kebantenan, yang dibeli oleh Raden Saleh dari masarakat yang tinggal di Kebantenan, Bekasi. Prasasti ini ditulis dengan aksara dan bahasa Sunda Kuna. Kini disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris E.1, E2, E.3, E.4, dan E.5). Isinya berupa piteket (pangéling-éling = peringatan) dari Sri Baduga Maharaja kepada rakyatnya untuk menjaga wilayah – utamanya - Sunda Sembawa. Baja dan besi yang mengandung tulisan belum pernah ditemukan, meskipun besi merupakan logam yang dimanfaatkan oleh urang Sunda dari sejak zaman dahulu, utamanya untuk bahan bangunan, seperti yang terdapat dalam teks sewaka darma: “Tihangna beusi diukir, bahana beusi sagala, dihateupan beusi cina, disaréan ku maléla, didingdingan ku beusi kuning, lilinggana beusi panamar”.
Bujangga Manik menyebutnya batu tulis untuk tulisan pada batu. Terbilang banyak artefak yang masih ada tinggalannya. Prasasti Batu Tulis di Bogor, Prasasti Cibadak di Sukabumi, prasasti Kawali di Ciamis, berupa bukti nyata tulisan di atas batu ‘sastra munggu ring batu’ seperti yang tercantum dalam Dasa Wredi. Padung (kayu) yang mengandung tulisan belum diketemukan, meskipun sekarang kayu masih digunakan untuk menulis nama orang yang meninggal sebagai penanda kuburannya.
Naskah: Awi (Bambu), Lontar, dan Gebang (Nipah)
Tulisan ini bakal membahas media yang belum di bahas di atas. Utamanya, awi (bambu), lontar, dan gebang (nipah)– bisa dimasukkan dalam kategori naskah, yang secara isi, redaksi, dan fungsinya bisa dibedakan dan yang ditulis dalam media lainnya.Pejwa (JK peja) 'bambu' terdapat jejaknya dalam naskah Sunda Kuna. Di Perpustakaan Nasional ada tiga naskah dari awi téh, di antaranya: Sanghyang Jati Maha Pitutur (SJMP, koropak 426 C), Kaleupasan (koropak 426 B ), dan Een Bundel Tje Wichelstokjis (koropak 1212). Aksara yang digunakeun semuanya aksara Sunda Kuna, sedangkan bahasanya basa Sunda Kuna dan Jawa Kuna. Umunya isinya singkat, lebih singget dari yang ditulis pada lontar dan gebang. Contohnya SJMP hanya terdapat 6 wilah (3 baris/wilah), Kaleupasan hanya 31 wilah (1 baris/wilah, isinya hanya 28 kalimat). Hingga saat ini, naskah dari bambu, utamanya yang berada di PNRI, belum ada yang diteliti secara mendalam!
Daun lontar merupakan media yang paling banyak digunakan untuk menulis naskah Sunda Kuna. Model aksaranya yaitu aksara Sunda Kuna, hanya naskah ‘Kala Purbaka’ (kropak 506) uang menggunakan aksara Buda (corak Merapi Merbabu). Contoh-contoh tulisan yang ditulis pada lontar di antaranya ‘Sewaka Darma’, ‘Carita Parahiyangan’, ‘Carita Purnawijaya’, ‘Bujangga Manik’, dan sebagainya.
Ayatrohaedi menyebut gebang (Corypha utan), sedangkan Atja menyebutnya daun rumbia (Metroxylon sagu) untu media yang oleh para ahli sekarang disebut daun nipah (Nypa fructican). Antara gebang, rumbia dan nipah hanya beda dalam nama spesiesnya saja, karena kelompoknya sama, yaitu palem. Gebang leubih tipis daripada lontar, warnanya leuwih pucat, coklat agak kuning, serta ditulis menggunakan tinta.
Antara lontar dan gebang memiliki konsep yang berbeda. Dalam naskah menerangkan bahwatulisan di atas lontar dinamai carik ‘gurat/garis’. Tulisan pada gebang dinamai ceumeung ‘hitam’. Dapat dimengerti, tulisan pada lontar digores menggunakan péso pangot, juga tidak hitam (hitam didapat dengan cara menggosokkan kemiring yang dibakar/di-grill), sedengkan gebang dinamai ceumeung ‘hitam’ disebabkan ditulis menggunakan tintan hitam, yang warnanya langsung terlihat, kontras dengan media yang dijadikeun alas tulisan.
Berdasarkan konsep Dasa Wredi, antara lontar dan gebang memiliki fungsi yang berbeda pula. Lontar “aya éta meunang utama, kénana lain pikabuyutaneun”. Kalimat ini mengandung arti, bahwa tulisan pada lontar isinya bukan untuk kabuyutan. Tegasnya, untuk masyarakat yang lebih luas, masarakat umum. Jika melihat bukti yang sampai pada kita sekarang ini, naskah-naskah dari daun lontar berbentuk puisi - misalnya Bujangga Manik, Sri Ajñana, Pantun Ramayana, Carita Purnawijaya, dan Séwaka Darma – yang besar kemungkinan dibacakan dalam bentuk pantun. Jadi ditampilkan yang sifatnya lebih populer bagi masyarakat.
Secara isi – meskipun ada pengecualian – sepintas naskah lontar mengandung ‘alur cerita’ dan 'tokoh’ yang dilakonkan. Meskipun isinya berupa teks kaagamaan (tutur), terasa adanya alur carita. Teks Sri Ajñana, misalnya. Ceritanya memiliki alur cerita yang digelardari awal Sri Ajñana turun ke dunia akibat melakukan dosa, mencari jalan untuk kembali ke kahyangan, hingga mendapati keadaan kaleupasan dari segala macam cobaan. Selain itu, naskah lontar penuh dengan autran baku sastra, gaya bahasanya lebih kaya dengan metafora, purwakanti (irama bahasa), dan paralelisme. Karena ditulis dalam bentuk puisi.
Berbeda lagi dengan naskah gebang, berdasarkan penelitian terkini, semuanya ditulis dalan bentuk prosa didaktis. Merupakan ajaran mahaguru kepada sang séwaka darma, muridnya, saperti yang terdapat pada teks Sanghyang Hayu dan Serat Déwa Buda. Naskah gebang fungsinya untuk kabuyutan ‘Ini ma iña pikabuyutaneun’, hasil dari tapa para wiku pandita. Jelasnya, digunakan untuk lingkungan yang lebih khusus, yaitu di kabuyutan.
Dari bahasan di atas, jelas bahwa dasa wredi, merupakan ciri kasadaran karuhun urang Sunda terhadap budaya lieterasi (tulis menulis) yang sangat besar perhatiannya.
Leuwih luangan, kurang tinabeuhan. Pun.
Diadaptasi dari Aditia Gunawan, Filolog Muda Indonesia