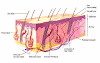|
| Air Terjun. Ilustrasi: pixabay.com |
[Historiana] - Oleh Alam Wangsa Ungkara. Unsur air merupakan hal yang sangat penting dalam pembinaan permukiman dalam skala makro. Menurut geomantik Jawa, kota harus didirikan di daerah yang cukup air. Penguasa yang akan mendirikan sebuah kota baru harus dapat menunjukkan kemampuannya di bidang irigasi dan drainase. Hal itu juga merupakan tantangan bagi penguasa untuk menaklukkan alam bebas guna mensejahterakan pengikutnya (Santoso, 2008: 167).
Air memegang peran penting dalam konsep kekuasaan. Pada masyarakat petani, air merupakan unsur vital untuk manusia dan pertanian. Sistem pengairan yang dilakukannya menimbulkan sistem kepemimpinan. Teori Oriental Despotism yang diajukan Karl Wittfogel, berisi tentang hydraulic society yang diambil dari studi tentang adanya despotisme dalam masyarakat pengguna air sungai di sekitar sungai-sungai Nil, Indus, dan Yang Tse Kiang. Di sana bisa muncul raja yang berkuasa mutlak untuk membagikan air (Wittfogel, 1957: 25). Secara tradisional, masyarakat Bali mengenal sistem organisasi subak untuk mengatur air (Geria, et al., 2019).
Dalam sejarah kuno Jawa Barat, di dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa pada tanggal 8 paro-petang bulan Phalguna dimulai penggalian Sungai Gomati yang mengalir di lahan tempat tinggal Sang Pendeta nenek Sang Purnawarman (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 52-53). Prasasti Tugu mengisyaratkan bahwa air, baik untuk irigasi maupun prasarana transportasi, merupakan unsur penting dalam melanggengkan kekuasaan Raja Purnawarman. Aktivitas penyediaan air juga dilakukan oleh Raja Wastukancana. Pada prasasti Kawali I disebutkan bahwa Prabu Raja Wastu membuat parit irigasi di sekeliling kota (Nastiti dan Djafar, 2016).
Pada masa kolonial, salah satu usaha para bupati untuk mempertahankan kekuasaan tradisionalnya terhadap rakyat dapat dilakukan melalui proyek-proyek yang ada hubungannya dengan air. Air secara tidak langsung dijadikan senjata untuk melawan pemerintah kolonial, di lain sisi untuk merangkul rakyat pribumi. Bupati Galuh, telah membangun prasarana pertanian dan perkebunan dalam rangka melawan pemerintah kolonial. Pada 1677 di daerah Priangan diterapkan Preangerstelsel. Para bupati diperintahkan mengharuskan rakyatnya untuk menanam kopi. Di Kabupaten Galuh, rakyat selain dipaksa menanam kopi juga diharuskan menanam nila. Bupati Galuh menolak dan memerintahkan rakyat untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan. Bangunan untuk kesejahteraan rakyat dibuat antara lain saluran air dan bendungan untuk irigasi sawah. Areal persawahan baru dibuka di mana-mana. Selain bersawah, Kangjeng Prabu memerintahkan rakyat untuk menanam kelapa. Setiap calon pasangan yang akan menikah diwajibkan membawa dua butir tunas kelapa (kitri) untuk ditanam di halaman rumahnya. Dengan cara seperti itu perkebunan kelapa mengalami perkembangan pesat sehingga dikenallah Ciamis sebagai gudang kelapa (Lubis, 2013). Bendungan dan saluran irigasi yang dibuat oleh Kangjeng Prabu antara lain adalah bendungan Nagawiru. Bendungan ini membendung Ci Leueur di perbatasan Desa Sukajadi dan Imbanegara, Kecamatan Imbanegara, Ciamis. Struktur bendungan berupa check dam yang membendung sungai sehingga permukaan air naik. Struktur check dam dari susunan batu kali berbentuk persegi (Saptono, 2018).
Dalam masyarakat primordial pertanian, air adalah kehidupan. Tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Cara berpikir petani adalah cara berpikir pertanian. Nilai tertinggi kehidupan adalah air untuk pertanian. Air hujan, sungai, letak tanah, kesuburan tanaman, hama, mata air, hutan, dan gunung adalah sistem pengetahuan mereka yang utama. Masyarakat peladang dan masyarakat penyawah sedikit berbeda dalam memahami air. Masyarakat peladang sangat menghargai air hujan sedangkan penyawah cenderung lebih mementingkan sungai. Meskipun demikian kedua kelompok masyarakat ini sadar sama-sama memelihara hutan dan sungai untuk menjaga air. Pada masyarakat Sunda, sumur jarang dikenal. Mereka cenderung memanfaatkan mata air di tepi sungai atau batu-batu cadas di tebing pinggir hutan. Dalam konsep dewa-dewa (hyang), masyarakat Baduy Sang Hyang Tunggal merupakan dewa tertinggi. Dia berputrakan 7 batara di antaranya adalah Batara Patanjala sebagai dewa air (Sumardjo, 2011: 71-73).
Kaitan antara unsur air dengan pertanian di dalam Naskah Cibeureum yang perlu dicermati adalah istilah ngabedah situ. Pekerjaan mirip ngabedah situ juga pernah dilakukan oleh Dalem R.A.A. Wiratanuningrat pada tahun 1925 membuka (ngabukbak) Rawa Lakbok untuk dijadikan area pesawahan yang luasnya 30.000 bau. Peristiwa ini tertuang di dalam naskah Ngabukbak Lakbok yang ditulis oleh R. Muhammad Sabri Wiraatmadja. Naskah kuno berupa buku tulis bergaris. Teks berupa tulisan tangan beraksara Arab pegon, Sunda, dan Latin. Isi teks merupakan catatan peristiwa sejak mulai dibukanya rawa hingga bermanfaat (Bastaman, 2004). Berdasarkan Naskah Cibeureum dan Naskah Ngabukbak Lakbok, ngabedah dapat diartikan membuka kawasan rawa yang semula tidak dimanfaatkan masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Pemanfaatan di Rawa Lakbok cenderung untuk usaha pertanian, sedangkan di Situ Cibeureum untuk memelihara ikan di samping juga untuk mengairi sawah.
Pembukaan Situ Cibeureum menurut Naskah Cibeureum dilakukan oleh Embah Entol, sedangkan menurut cerita lisan yang berkembang adalah Bagus Jamri. Perbedaan ini dapat dipahami bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan dan data, Embah Entol sebagai pemrakarsa sedangkan Bagus Jamri adalah pelaksana. Di dalam Naskah Cibeureum disebutkan bahwa pengerjaan dilakukan oleh Sugri.
Referensi
- Bastaman, H. D. 2004. "R.A.A. Wiratanuningrat Jeung Rawa Lakbok: Dumasar kana Naskah 'Ngabukbak Lakbok' karya R. Muh. Sabri Wiraatmadja". In Bupati di Priangan dan Kajian Lainnya Mengenai Budaya Sunda. Seri Sundalana 3 (pp.67–88). Bandung.
- Geria, I. M., Sumardjo, nfn, Sutjahjo, S. H., Widiatmaka, nfn, & Kurniawan, R. 2019. "Subak sebagai Benteng Konservasi Peradaban Bali". Jurnal AMERTA, 37(1), 39–54.
- Lubis, N. H. 2013. "Sejarah Kabupaten Ciamis". Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Nastiti, T. S., & Djafar, H. 2016. "Prasasti-prasasti dari Masa Hindu-Buddha (Abad ke-12 - 16 Masehi) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat". PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi, 5(2), 101–116.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 2009a. "Sejarah Nasional Indonesia I. Zaman Prasejarah". Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 2009b. "Sejarah Nasional Indonesia II, Zaman Kuno". Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, J. 2008. "Arsitektur-kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa". Jakarta: Centropolis - Magister Teknik Perencanaan Universitas Tarumanagara.
- Saptono, N. 2018. "Tata Ruang Kota Ciamis Pasca perdagangan Dunia Abad Ke-19 – 20". Panalungtik, 1(1), 41–60.
- Sumardjo, J. 2011. "Sunda: Pola Rasionalitas Budaya". Bandung: Kelir.
- Widyastuti, Endang dan Nanang Saptono. "Makam-makam Kuno di Tasikmalaya: Latar Belakang Konsep dan Tokoh". Jurnal PANALUNGTIK: Jurnal Arkeologi Balai Arkeologi Jawa Barate-ISSN: 2621-928X Vol. 2(1), Juni 2019, pp 17 – 32