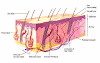Yang menjadi polemik dalam naskah ini adalah tentang pendiri Majapahit, yaitu Rahadyan Wijaya yang disebut sebagai putra pasangan Rakeyan Jayadarma dari Kerajaan Sunda Galuh dengan Dyah Lembu Tal dari Kerajaan Singhasari. Dengan kata lain, Dyah Lembu Tal disebut sebagai wanita yang memiliki nama lain Dewi Singhamurti. Anehnya, naskah tersebut secara tidak konsisten menyebut Dewi Singhamurti adalah putri Mahisa Campaka pada halaman 58, tapi kemudian berubah pada halaman 60, yaitu Mahisa Campaka disebut sebagai mertua Dewi Singhamurti.
Sebagian para ahli sejarah menyatakan bahwa Naskah Wangsakerta bukan naskah kuno, tetapi karya tulis modern dari abad ke-20 yang menggunakan bahasa Jawa Kuno, bahkan terlalu kuno untuk ukuran abad ke-17. Isi dari naskah tersebut juga memiliki banyak kemiripan dengan hasil penelitian de Casparis, N.J. Krom, ataupun E. Dubois. Selain itu, lembaran naskah tersebut setelah digosok luntur warnanya dan setelah diamati ternyata merupakan kertas manila yang diolah dengan semacam zat kimia supaya menyerupai kertas kuno. Dengan demikian, itu berarti Naskah Wangsakerta tidak lebih tua daripada Babad Tanah Jawi, tetapi justru lebih muda usianya.
Naskah Wangsakerta yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah putra Sunda kiranya terinspirasi oleh kisah Jaka Sesuruh yang disebut berasal dari Pajajaran menurut Babad Tanah Jawi. Kisah tersebut kemudian diolah dan dipadukan dengan berita dari naskah kuno Carita Parahyangan. Perlu diketahui, bahwa dalam Carita Parahyangan sama sekali tidak disinggung soal Raden Wijaya. Itu artinya, satu-satunya naskah yang menyebut bahwa Raden Wijaya putra Sunda adalah Naskah Wangsakerta yang kontroversial tersebut.
Babad Tanah Jawi mengisahkan Jaka Sesuruh menyingkir ke timur meninggalkan Pajajaran menuju Singasari dibantu seorang janda bernama Nyai Randa Kaligunting. Maka, si penulis Naskah Wangsakerta pun memodifikasi kisah ini dengan menyebutkan bahwa setelah Rakeyan Jayadarma meninggal, Dyah Lembu Tal menjadi janda dan membawa Raden Wijaya meninggalkan Sunda Galuh menuju ke Singhasari. Dengan kata lain, Jaka Sesuruh ditafsirkan menjadi Raden Wijaya, sedangkan Nyai Randa Kaligunting ditafsirkan menjadi Dyah Lembu Tal.
Sungguh mengagumkan, penulis Naskah Wangsakerta sangat jenius karena imajinasinya yang mampu meramu berita sejarah dari berbagai sumber dan merangkainya kembali menjadi satu urutan menggunakan bahasa Jawa Kuno, dengan mencatut nama Pangeran Wangsakerta sebagai penulisnya. Sayang sekali, usahanya ini justru mengundang kecurigaan karena bahasa dalam naskah tersebut terlalu kuno untuk ukuran abad ke-17. Bukankah pada pembukaan Naskah Wangsakerta tertulis bahwa naskah itu disusun pada tahun 1682, tapi mengapa bahasa yang digunakan berasal dari abad ke-14? Selain itu, pada lembaran-lembaran Naskah Wangsakerta juga terdapat bekas tulisan pensil yang dihapus dengan penghapus karet kemudian ditindih tinta, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Pangeran Wangsakerta.
Dengan demikian, penulis Naskah Wangsakerta adalah sejarawan abad ke-20 yang telah mempelajari hasil penelitian para ahli seperti de Casparis, N.J. Krom, E. Dubois, dan sebagainya, lalu memadukannya dengan Pararaton, Nagarakretagama, Carita Parahyangan, dan Babad Tanah Jawi, menjadi sebuah naskah sejarah berbahasa Jawa Kuno, dengan mencatut nama Pangeran Wangsakerta yang merupakan pakar sejarah dari Kesultanan Cirebon abad ke-17.
Naskah Wangsakerta dengan berani menyebut Dyah Lembu Tal sebagai wanita, namun kurang konsisten karena di halaman 58 ia disebut sebagai putri Mahisa Campaka, tetapi di halaman 60 ditulis sebagai menantu Mahisa Campaka. Pada halaman 58 bunyinya seperti ini : “déwi singhamurti ngaranira yata putrining mahisa campaka mituhu sang mahākawi jawa ikang déwi singhamurti ngaranira dyah lembu tal sakéng pakurenira déwi singhamurti lawan rakryan jayadarma manak ta sira sang nararya sanggramawijaya”. Sedangkan dalam halaman 60 demikian bunyinya : “déwi singhamurti lawan putranira yatiku radén wijaya kala raray wangsuling bhumya nagaranira hurip lawan ramatuhanira mahisa campaka”.
Sepertinya si penulis terjebak pada gelar Dyah yang dipakai Lembu Tal. Memang pada zaman modern nama Dyah identik dengan kaum wanita. Akan tetapi, pada zaman Majapahit sebutan Dyah adalah gelar kebangsawanan yang bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Dalam sejumlah prasasti peninggalan Majapahit banyak dijumpai nama pangeran dan pejabat yang bergelar dyah, misalnya Dyah Wijaya, Dyah Halayudha, Dyah Pamasi, Dyah Puruseswara, Dyah Hayamwuruk, Dyah Ranawijaya, Dyah Kertawijaya, Dyah Wijayakumara, Dyah Suraprabhawa, dan sebagainya. Itu artinya, gelar dyah dalam tradisi Jawa Kuno bukan milik kaum wanita saja.
Kemudian mari kita lihat nama Lembu Tal. Dalam tradisi Jawa nama Lembu, Mahisa, Kebo, Gajah, dan Kuda selalu digunakan untuk kaum laki-laki sebagai simbol kejantanan. Sebut saja nama Lembu Sora, Lembu Nala, Lembu Amiluhur, Lembu Amijaya, Mahisa Anabrang, Mahisa Mundarang, Kebo Hijo, Kebo Kenanga, Kebo Kanigara, Gajah Mada, Gajah Biru, Gajah Pagon, Kuda Anjampyani, Kuda Amreta dan sebagainya. Semuanya adalah kaum laki-laki. Dengan demikian, nama Lembu Tal sudah pasti juga laki-laki, karena tidak ada ceritanya orang Jawa memberikan nama Lembu untuk anak perempuan.
Sekarang mari kita cari naskah mana yang mula-mula menyebut nama Dyah Lembu Tal, yang diubah jenis kelaminnya oleh penulis Naskah Wangsakerta itu. Dalam kakimpoi Nagarakretagama bait ke-174 karya Prapanca, kita jumpai kalimat sebagai berikut :
“sri narasinghamurttyaweka ri dyah lembu tal susrama sang wireng laga dhinarmma ri mireng boddha pratista pageh”
Kalimat tersebut diterjemahkan oleh Prof. Ketut Riana sebagai berikut : “Sri Narasinghamurti ayah Dyah Lembu Tal yang terpuji, pemberani dalam pertempuran diabadikan di mireng dalam wujud arca Buddha”.
Terjemahan ini dimanfaatkan oleh para pendukung Naskah Wangsakerta bahwa tokoh yang dipuji Prapanca sebagai “pemberani dalam pertempuran” adalah Narasinghamurti (Mahisa Campaka), bukan Lembu Tal.
Sayang sekali, terjemahan Prof. Ketut Riana tersebut sedikit keliru, karena kata “aweka” artinya adalah “berputra”, bukan “ayah”. Sehingga, kalimat “sri narasinghamurttyaweka ri dyah lembu tal” harusnya diterjemahkan “Sri Narasinghamurti berputra Dyah Lembu Tal”, bukan diterjemahkan “Sri Narasinghamurti ayah Dyah Lembu Tal”.
Maka, kalimat terjemahan selengkapnya yang lebih tepat adalah : “Sri Narasinghamurti berputra Dyah Lembu Tal terpuji yang pemberani dalam pertarungan dan didharmakan di Mireng dengan arca Buddha ditegakkan di sana.”
Dengan demikian, pujian “sang wireng laga” ditujukan untuk Dyah Lembu Tal, bukan untuk Sri Narasinghamurti. Itu artinya, Dyah Lembu Tal adalah seorang laki-laki, karena Prapanca dalam Nagarakrtagama lebih suka memuji para wanita dalam hal kecantikannya, bukan keberaniannya.