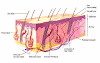[Historiana] - Hilangnya nalar kritis masyarakat, semakin menjadi pasca pemilu 2019. Demikian Abdul Aziz Faradi menuliskannya pada "Teori-teori Kebenaran filsafat". Sebuah kondisi yang ditengarai oleh para pengamat politik sebagai dampak dari budaya post-truth politic (politik pascakebenaran).
Bahaya yang muncul dari budaya politik semacam ini adalah hilangnya daya kritis dan rasionalitas masyarakat. Indikator yang paling tampak dari budaya politik pascakebenaran dalam pemilihan umum 2019 adalah intensitas penggunaan isu agama dalam meraih suara partisan politik. Agama merupakan isu sensitif yang menjadi appeal of passion dalam diskursus politik pascakebenaran.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, politik pascakebenaran memiliki arah yang bertentangan dengan tradisi filsafat. Di satu sisi, budaya politik pascakebenaran lebih mengutamakan terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk mencapai target politik tanpa mengindahkan kebenaran faktual. Sementara di sisi lain, filsafat sejak era Yunani kuno selalu fokus untuk mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi arah kehidupan manusia.
Di tengah sengkarut iklim politik yang tidak berlandaskan pada kebenaran faktual, kondisi masyarakat diperparah dengan minimnya, (untuk tidak mengatakan tidak ada), basis epistemologis dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran. Masyarakat tidak bisa memberikan garis demarkasi yang jelas antara kebenaran dan bukan karena terbiasa menerima kebenaran sebagai sebuah produk jadi. Di sinilah kemudian letak tugas penting filsafat untuk mengembalikan nalar kritis dan rasional masyarakat.
Secara garis besar pengertian filsafat dapat dipilah ke dalam dua kategori; (1) filsafat sebagai sebuah proses berpikir dan (2) filsafat sebagai sebuah produk hasil pemikiran. Filsafat sendiri pada saat yang bersamaan dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu (a group of theories) ataupun metode berpikir (systems of thought). Dengan demikian, filsafat tidak boleh hanya menjadi sebuah rumusan tentang kebenaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga harus menjadi bekal bagi setiap individu dalam mengkritisi segala konsepsi yang diklaim sebagai kebenaran. Dengan kata lain, filsafat tidak hanya mewujud dalam rumusan kebenaran, tetapi harus harus berperan aktif dalam proses merumuskan kebenaran itu sendiri.
Kendati demikian, kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Silang pendapat antara rasionalis dan empirisis dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia. Dalam diri manusia, manakah dia antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia? Selain cakupan dan validitas pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik, dalam salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi.
Berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat.
1. Teori Korespondensi
Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta obyektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada. ederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Oleh karena sifatnya yang mengandalkan pengalaman inderawi dalam menangkap fakta, maka teori ini menjadi teori yang digunakan oleh para empirisis. Sebagai contoh, sebuah pernyataan “di luar terjadi hujan”dianggap benar jika terdapat fakta obyektif di luar sana benar-benar terjadi hujan.Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Prinsip verifikasi ini berguna untuk mengatasi kesalahan yang mungkin timbul pada setiap individu dalam menangkap kesan-kesan inderawi. Gula yang sejatinya manis akan terasa pahit di indera pengecap orang yang sedang sakit atau memiliki gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengujian terhadap fakta harus dilakukan secara terukur, berulang-ulang dan melibatkan sebanyak mungkin responden. Prinsip verifikasi ini banyak digunakan dalam metode saintifik untuk mengatasi kelemahan inderawi dalam menangkap fenomena faktual.
2. Teori Koherensi
Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum (general truth). Matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar. Kita tidak perlu menunggu hingga esok pagi untuk membuktikan secara faktual bahwa matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Aksioma atau postulat adalah sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena sifat itulah ia dijadikan sebagai dasar dalam disiplin ilmu matematika dan bisa digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan lain benar atau tidak.Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan (kontradiksi) antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi.
Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada, sedangkan pada teori koherensi pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Contoh lainnya, seseorang memberi pernyataan bahwa di dalam kolam alun-alun kota terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup. Menurut teori korespondensi, untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau tidak, kita harus menunggu fakta apakah di dalam kolam tersebut terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup atau tidak. Sementara menurut teori koherensi, tanpa menunggu fakta, kita bisa meentukan pernyataan orang tersebut tidak benar karena bertentangan dengan aksioma yang sudah ada sebelumnya bahwa ikan hiu adalah jenis ikan air asin (laut). Tidak logis jika ikan air asin bisa hidup dalam air kolam alun-alun kota yang merupakan kolam air tawar.
3. Teori Pragmatis
Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta obyektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan obyek pengetahuan metafisik.Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan.
Terkait dengan teori kebenaran, Charles Pierce, salah satu tokoh pragmatisme menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memusaskan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Beragamnya sudut pandang dalam menentukan hasil yang memuaskan akan berujung pada beragamnya standar kebenaran. Kebenaran menurut saya belum tentu benar menurut orang lain karena apa yang memuaskan bagi saya belum tentu memuaskan bagi orang lain. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat teori pragmatisme rentan terjebak dalam relativisme. Inilah salah satu dari beberapa kritik yang diarahkan pada teori pragmatisme.
4. Teori Performatif
Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J. L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika Bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran (truth-evaluable) secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya.Sementara itu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses fakta yang terjadi. Selain keterbatasan akses kepada fakta, ketidakbisaan sebuah ujaran untuk dibuktikan juga bisa disebabkan karena sebuah ujaran berkaitan dengn kondisi atau aktivitas mental seseorang. Ketika seseorang berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama kelak di kemudian hari, kita tidak bisa membuktikan apakah ia berjanji sungguh-sungguh seperti yang ia ucapkan atau tidak. Kesungguhan dalam janji adalah aktivitas mental dan oleh karena itu tidak bisa dibuktikan.
Untuk hal-hal ini, Austin mengenalkan jenis ujaran performatif. Ujaran-ujaran ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta obyektif maupun konsistensi logis yang dikandungnya, melainkan berkaitan dengan layak atau tidaknya ujaran tersebut dikeluarkan oleh sang penutur. Atas dasar itulah kebenaran performatif mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenarannya. Otoritas ini bisa dimaknai sebagai adanya wewenang, kepakaran atau kompetensi sang penutur dalam hal yang diungkapkan dalam ujarannya.
Contoh yang paling umum dari jenis kebenaran performatif adalah penentuan awal bulan Ramadan. Awal masuknya bulan Ramadan ditentukan melalui fakta munculnya hilal (bulan muda) yang merupakan awal pergantian bulan yang sekaligus menjadi pertanda dimulainya ibadah puasa bagi umat muslim. Kendati kemunculan hilal merupakan fakta obyektif dijadikan sebagai dasar kebenaran penentuan awal Ramadan (sebagaimana pembuktian pada teori korespondensi), terdapat keterbatasan akses bagi orang awam untuk membuktikan melalui pencerapan inderawi. Jatuhnya awal Ramadan tidak dibuktikan oleh masyarakat dengan menyaksikan langsung fakta kemunculan hilal, tetapi melalui pernyataan menteri Agama yang dianggap memiliki otoritas untuk menentukan awal Ramadan.
5. Teori Konsensus
Teori kebenaran consensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Penulis buku The Structure of Scientific Revolutions ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya, akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma (shifting paradigm) dalam masyarakat ilmiah. Singkat kata, perkembangan imu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat (social acceptance) terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah.Berdasarkan konsepsi Kuhn di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan (konsensus) dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Inilah yang disebut teori kebenaran konsensus. Teori ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Jurgen Habermas melalui konsep pemikirannya tentang komunikasi rasional. Senada dengan Kuhn, menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus.
Referensi
- Austin, John Langshaw, How to Do Things with Words, (Oxford: Clasendon Press, 1962)
- Ayer, Albert J. dan J,O’Grady, A Dictionary of Philosophical Quotations, (Oxford: Blackwell Publishers, 1994).
- Gallagher, Kenneth T., The Philosophy of Knowledge (Epistemologi,Filsafat Pengetahuan), terj. P.
- Hardono Hadi, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1994).
- James, William (Ed.), Pragmatism: A New Name for Same Old Ways of Thinking, (New York: Longman Green and Co., 1907).
- Kattsoff, Louis, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004). Kuhn, Thomas. The Structure of Scientifc Revolution, (Chicago: University of Chicago Press, 1962).
- Postman, Neil, Technopoly, The Surrender of Culture to Technology, (New York: Vintage Books, 1993).
- Russell, Bertrand, Sejarah Filsafat Baratdan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuni hingga Sekarang, terj. Sigi Jatmiko dkk. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004).
- Suseno, Franz Magniz, 12 Tokoh Abad ke-20, (Yogyakarta: Kanisisus, 2000).
- Tiffin, John dan Nobuyashi Terashima, Hypereality, Paradigm for The Third Millenium, (London, New York: Routledge, 2005).
- Titus, Harold K., Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Zaprulkhan, Filsafat Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
Sumber: Abdul Aziz Faradi: Teori-Teori Kebenaran Dalam Filsafat: Urgensi dan Signifikansinya dalam Upaya Pemberantasan Hoaks. Jurnal Kontemplasi, Vol. 07, No.01, Juli 2019.