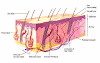|
| Prasasti Poh Lempeng 1A (atas) dan Lempeng 2B (bawah) (Dok. digitalcollections.universiteitleiden.nl) |
[Historiana] - Prasasti Poh atau Prasasti Randoesari I pertama kali ditelaah secara kritis oleh W.F Stutterheim pada tahun 1940. Prasasti Poh merupakan 2 lempeng prasasti tembaga yang ditemukan di dukuh Plembon, Kelurahan Randusari, Gondangwinangun, Klaten. Dinamai sebagai prasasti Poh karena berisi tentang penetapan wanua Poh menjadi sima yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung.
Artikel ini dikutip dari "Pemakaian Istilah Bahasa Sanskerta Pada Nama Diri Di Dalam Prasasti Poh (827 Çaka): Tinjauan Perspektif Identitas" hasil penelitian Kayato Hardani, Mahasiswa Program Magister Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Berkala Arkeologi Vol.38 Edisi No.2 November 2018 dari laman core.ac.id.
Penetapan suatu wilayah menjadi sima dapat merupakan anugerah raja kepada seseorang yang telah berjasa atau untuk memelihara suatu bangunan suci. Pemberian status sima juga dilakukan agar wilayah yang kurang penting menjadi lebih menarik bagi para petani yang pada akhirnya dapat memperluas pemukiman yang sudah mantap menjadi wilayah yang strategis (Christie,1989a:6). Selain itu, penetapan sebagai sima juga dimaksudkan sebagai upaya pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah adalah dengan pengembangan pemukiman desa atau watak atau juga berupa pengembangan wilayah pertanian atau tegalan (Tjahjono dan Rangkuti, 1998:46).
Agar kita lebih mudah memahami situasi dan kondisi zaman Mataram kuno, berikut ini tabel sederhana mengenai Wilayah dan Struktur Pemerintahan Mataram Kuno.
 |
| Struktur Birokrasi Mataram Kuno oleh: Alam Wangsa Ungkara |
Pada setiap upacara penetapan sima selalu menghadirkan pejabat beserta sejumlah warga desa atau anak wanua sebagai saksi yang disertai dengan pesta dan diakhiri dengan pemberian pasek-pasek sebagai persembahan yang berwujud bahan pakaian, uang emas dan perak. Khusus bagi hadirin dari kalangan warga desa seringkali berasal dari desa sekitar wilayah (desa tpi i siring) yang ditetapkan sebagai sima. Pesta di dalam sebuah upacara sima semacam ini mengindikasikan gejala arkaik pesta jasa khas Nusantara. Di dalam Prasasti Poh ini pula kita menjumpai nama-nama pejabat dan warga desa yang menghadiri dalam pesta sekaligus sebagai penerima pasek-pasek tersebut.
Upacara penetapan sima sebagaimana yang dituliskan di dalam prasasti dapat diamati sejumlah gejala sosial yang membeku dalam teks prasasti. Hal tersebut lebih berkenaan dengan sifat prasasti sebagai wujud budaya materi yang menghadirkan prasasti sebagai artefak yang memiliki makna dan telah dihayati bersama oleh kelompok sosial atau komunitas masyarakat. Penggunaan bahasa di dalam prasasti telah menjadikan prasasti sebagai budaya materi yang di dalamnya mengandung ide gagasan.
Salah satu hal yang menarik dijumpai di dalam gejala kebahasaan prasasti adalah penggunaan kosa kata serapan Bahasa Sanskerta pada prasasti abad ke-9 hingga 10 Masehi. Nama diri (antroponimi) yang menggunakan unsur kata pinjaman Bahasa Sanskerta menjadi gejala kebudayaan yang menarik. Nama diri adalah nama yang diberikan semenjak lahir (garbhanama) oleh orang tua bayi yang seringkali menunjukkan posisi seseorang secara hirarki dalam stratifikasi sosial masyarakat masa itu. Pemarkah yang sering dipakai sebagai pembeda tersebut adalah kehadiran partikel persona (dyah, pu, si dan sang) yang muncul di depan nama diri.
Pada masa Jawa Kuna terdapat beberapa istilah di dalam Bahasa Jawa Kuna yang berkenaan dengan istilah “nama diri” yang dijumpai di dalam naskah dan prasasti, yakni aran, nāma, kěkasir atau kasir-kasir, pañji, puspapāta, pasěńgahan atau pasańguhan (Casparis, 1986: 10).
Nama Diri Hadirin Upacara Sima Wanua Poh Tahun 907 Masehi
Nama diri dalam masyarakat Jawa Kuna yang terlihat dalam prasasti menampakkan kecenderungan gejala patriarkhi dalam kehidupan sosialnya. Selain itu juga tampak adanya indikasi penggunaan alur ayah sebagai penanda terlihat dari persentase penggunaan kata rama ni (ayahnya) lebih besar dibanding penggunaan inang ni (ibunya). Menariknya kata ‘rama’ secara etimologis berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti ayah, kata pinjaman ini kemudian disejajarkan dengan kosakata asli Jawa ‘inang’ yang pada dasarnya adalah bentuk retensi dari kosakata Proto Austronesia (PAN) *inaŋ. Adapun bentuk ‘ni’ adalah bentuk pewarisan Bahasa Jawa Kuna dari bahasa PAN sebagai penunjuk konstruksi genetif (pemilik). Bentuk ‘ni’ terjadi melalui pelesapan bunyi akhir bentuk Austronesia *nia (Mahsun,2010:202). Bentuk ini pula yang masih bertahan pada masa Jawa modern ‘ne’ seperti dalam kata bapakne (ayahnya).
 |
| Nama Diri dalam Prasasti Poh Sumber: Kayato Hardani, Berkala Arkeologi Vol.38 Edisi No.2 November 2018 |
 |
| Tabel Persentase berdasarkan gelar Sumber: Kayato Hardani, Berkala Arkeologi Vol.38 Edisi No.2 November 2018 |
Bermula dari nama para hadirin yang hadir sebagai saksi di dalam upacara penetapan sima dapat diketahui fakta-fakta sosial yang hidup berkembang pada masa itu. Baik itu saksi dari kalangan pejabat kerajaan, pejabat watak maupun penduduk desa/seniman. Di dalam Prasasti Poh terlihat adanya beberapa penggunaan formula nama untuk mengidentifikasi persona yang berbeda dan menunjukkan pengelompokan-pengelompokan tertentu. Penentuan formula-formula tersebut lebih didasarkan pada penyebutan partikel penyebut yang secara langsung ditulis di depan nama diri. Berikut disajikan tabel tentang jenis formula yang dijumpai di dalam Prasasti Poh.
Selain itu secara kuantitatif formula tersebut apabila diklasifikasikan berdasar kategori jabatan administratif kerajaan, yakni pejabat kerajaan, pejabat tingkat watak, pejabat tingkat wanua, dan terakhir non pejabat (saksi dan seniman).
Selain itu juga disajikan tabel nama diri keseluruhan saksi yang jadir di dalam upacara penetapan sima yakni sebanyak 140 orang. Tabel-tabel tersebut dibedakan menjadi 4 kategori yakni pejabat kerajaan, pejabat watak, pejabat wanua dan non pejabat.
Data berupa nama diri yang dituliskan di dalam Prasasti Poh terlihat adanya struktur sosial yang terwujud di dalam pembagian jabatan yang terbagi menjadi 3 yakni pejabat tingkat kerajaan, pejabat tingkat watakdan pejabat tingkat wanua. Selain itu masih terdapat lagi beberapa orang yang bukan sebagai pejabat tetapi turut sebagai saksi (rāma tpi siring milu sākçīring manuçuk), yakni para rama marata dan seniman. Di dalam penyajian urutan daftar saksi yang menerima pasek-pasek dalam Prasasti Poh juga telah menunjukkan struktur yang dimulai dari Sri Maharaja sebagai orang yang terpenting dalam acara ini yang kemudian diakhiri oleh para ramadari desa sekeliling dan beberapa seniman yang diikutkan sebagai saksi.
 |
| Persentase Pejabat dan Nonpejabat dalam Prasasti Poh Sumber: Kayato Hardani, Berkala Arkeologi Vol.38 Edisi No.2 November 2018 |
Pada Tabel di atas, terlihat bahwa pejabat tingkat watak mempunyai prosentase lebih tinggi di dalam pemakaian frase Bahasa Sanskerta dalam nama diri, yakni 20 orang (14%) dari keseluruhan yang berjumlah 47 orang. Berdasarkan konstruksi terlihat jika nama diri yang dipakai adalah berupa wujud dasar, yakni dengan menggunakan kata atau nama dasar (monomorfemis). Hal tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat Jawa Modern yang penggunaan nama dirinya berwujud kompleks (polimorfemis) yakni nama dasar yang diberi imbuhan morfem lain.
Bentuk dasar dari nama yang dipakai antara pejabat kerajaan dan watak dengan pejabat wanua juga menunjukkan gejala yang menarik. Untuk nama diri pejabat kerajaan dan watak terlihat menggunakan frase-frase kongkret nama tokoh yang berakar dari mitologi agama Hindu dan Buddha seperti Suryya, Laksana dan Raghu. Konstruksi yang lain adalah penggabungan dua frase yang lebih kompleks semacam Wīrawikrama dan Çiwadhyāna. Pilihan frase maupun konstruksi nama para pejabat kerajaan dan watak menunjukkan pilihan-pilihan frase yang bermartabat.
Lain halnya dengan pejabat tingkat wanua yang lebih memilih frase-frase yang bersifat general seperti Buddhi, Suddha dan Mala. Terdapat satu hal yang menarik adalah terlihat di dalam nama diri Sri Maharaja yang menggunakan garbhanama khas Jawa Kuna, yakni Dyah Balitung. Secara leksikon frase “balitung” tidak memiliki makna namun ia tetap menggunakannya sebagai nama diri penguasa Mataram Kuna. Meski demikian Dyah Balitung untuk menunjukkan identitas yang berbeda dalam puncak stratifikasi sosial adalah dengan menggunakan gelar abhisekanama yang merupakan gambaran perwujudan dewa ke dalam tubuh raja yang menguasai kerajaan sebagai bagian makrokosmos.
 |
| Tabel Uraian nama Sansekerta dalam Prasasti Poh Kayato Hardani, Berkala Arkeologi Vol.38 Edisi No.2 November 2018 |
Nama diri yang dijumpai di dalam Prasasti Poh apabila diasumsikan sebagai garbhanama yang tetap dipakai semenjak pertama kali diberikan oleh sang orang tua sewaktu bayi hingga dewasa (menjadi pejabat), maka pemilihan dengan menggunakan Bahasa Sanskerta secara langsung juga berpengaruh pada makna yang dipilih atas nama diri mereka. Pejabat watak sejak lahir diidentifikasikan sebagai komunitas keluarga raja yang secara struktural dan perseptual dekat dengan raja sebagai perwujudan dewa, sehingga nama diri yang dipilih untuk mendefinisikan dirinya adalah sebagai bagian inti kosmos 'alam semesta' yakni lingkungan kerajaan sebagai pusat persentuhan dan perkembangan pengaruh India dengan agama Hindu dan Buddha.
Demikian sebaliknya di kalangan pejabat wanua yang pada dasarnya bukan kerabat raja serta secara lokasi jauh dari pusat kerajaan, intensitas penggunaan Bahasa Sanskerta di dalam nama diri sangat jarang. Di kalangan pejabat wanua dan non pejabat yang turut hadir dalam upacara hanya dijumpai 9 orang dengan menggunakan nama diri dengan unsur Bahasa Sanskerta dari keseluruhan 77 orang yang hadir (lihat Tabel Daftar Pejabat dan NonPejabat). Pemilihan secara leksikal pun dipilih makna yang lebih bersifat umum dan abstrak. Selain itu dari nama pejabat wanua dan saksi nonpejabat terlihat masih menganut konsep asli Jawa Kuna (atau Austronesia) yakni menggunakan formula “rama ni” atau “inang ni”. Hal tersebut juga terlihat dengan penggunaan nama diri yang tidak memiliki makna leksikal dalam bahasa Jawa Kuna. Meski demikian nama semacam itu dipahami secara komunal oleh masyarakat masa itu.
Telah dipahami bahwasanya pejabat watak berada pada stratifikasi kedua setelah pejabat kerajaan. Mereka pada umumnya juga masih kerabat raja (bangsawan) yang mempunyai kewenangan di daerah dalam struktur birokrasi kerajaan Mataram Kuna. Para pejabat watak ini pada saat itu adalah orang-orang middle rangedi dalam menerima dan menyerap pengaruh India. Edi Sedyawati (1986) mengatakan bahwa dominasi oleh kaum bangsawan dalam hal penerimaan pengaruh India dapat dikaitkan dengan asumsi bahwa budaya India pertama kali merasuk pada kalangan rajya yang kemudian mengembangkan budaya dengan berorientasi kepada pergaulan internasional (Sedyawati, 1986:36). Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal bahwa bahasa Sanskerta lebih dipakai dalam situasi resmi keagamaan dan dipelajari oleh orang terpelajar setidaknya paham akan baca tulis. Dengan melihat jabatan watak tersebut terdapat beberapa jabatan citralekha dan parujar yang merupakan jabatan yang menuntut kemampuan untuk baca tulis. Sehingga dari hal ini terlihat jika perolehan kosa kata dari Bahasa Sanskerta yang kemudian dipakai sebagai nama diri adalah dari aktivitas pendidikan.
Di dalam pemilihan nama oleh orang tua secara umum dapat dilakukan secara arbitrer dan nonarbitrer. Arbitrer adalah penamaan sekadar untuk membedakan dengan orang lain dan nama itu tidak diketahui asal muasal maknanya. Hal ini dalam prasasti dapat dilihat untuk nama-nama yang menggunakan kosa kata Bahasa Jawa Kuna yang tidak memiliki makna leksikal. Meski demikian ia tetap memiliki makna bagi pemberi dan pemilik nama. Makna sebuah nama bagaimanapun sederhananya sangat berarti sehingga seseorang mengabadikan dalam nama.
Penamaan secara nonarbitrer adalah memilih yang kata yang merupakan bagian dari tuturan atau kadangkala memiliki padanan dengan kosakata bahasa lain yang mengandung tujuan, harapan, cita-cita serta menggambarkan aspek historisitas. Sehingga umumnya penamaan semacam ini dijumpai maknanya secara leksikal. Melalui penguraian secara etimologis terhadap nama diri yang berasal dari bahasa Sanskerta juga dapat diketahui perbedaan pilihan kosakata yang dipakai oleh pejabat watak maupun pejabat wanua.
Pemberian nama merupakan salah satu upaya seseorang (orang tua) di dalam memandang dunianya yang dapat mengkomunikasikan antara alam pikiran, cita-cita, atau bahkan perkembangan lingkungan sosialnya. Salah satu contoh yang menarik terlihat adalah dari penggunaan nama yang dipakai oleh pejabat wanua yang secara eksplisit menunjukkan adanya perubahan budaya dalam memilih nama untuk anaknya. Seperti dalam nama si jabwah inang ni çuddhayang dengan jelas nama jabwah adalah nama asli Jawa Kuna yang tidak ada makna leksikalnya, sedangkan dia (si Jabwah) mempunyai anak yang dinamai dengan çuddhayang bermakna murni atau bersih. Dapat diperkirakan bahwa orang tua memberi nama dengan menggunakan kata Bahasa Sanskerta adalah terkait erat dengan motivasi dan dorongan, pola pikir dan respons budaya baru di dalam masyarakat.
Sumber: Hardani, Hardani. 2019. "Pemakaian Istilah Bahasa Sanskerta Pada Nama Diri Di Dalam Prasasti Poh (827 Çaka):Tinjauan Perspektif Identitas". core.ac.uk Diakses 4 Agustus 2020.
Sumber bacaan lebih lanjut:
- Christie, Jan Wisseman. 1989a. “ Raja dan Rama: Negara Klasik di Jawa Masa Awal ”, dalam Lorraine Gesick (ed.), Pusat, Simbol dan Hirarki Kekuasaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Christie, Jan Wisseman. 1989b. “Wanua, Thani, Paraduwan: The Disintegrating Village in Early Java”. Dalam Wolfgang Marschall (ed). Proceeding of the 7th European Colloqium on Indonesian and Malay Studies. Bern: Institut für Ethnologie.
- De Casparis, J.G. 1986. “Some Aspects of Proper Names in Ancient Java”, dalam CD. Grijns and S.O.Robson (eds), Cultural Contact And Textual Interpretation: Papers From TheFourth European Colloquium On Malay And Indonesian Studies, Held In Leiden In 1983, hlm. 8-18. Dordrecht/Cinnaminson: Foris. KITLV, Verhandelingen 115.
- Digitalcollections.universiteitleiden.nl. (2020) OD-14439 | Digital Collections. [Charter of Randusari (plate 1A). Inscription in Kawi script, language Old Javanese (see nos. 14440-14453)] OD-14439.
- Digitalcollections.universiteitleiden.nl. (2020). OD-14450 | Digital Collections. [Charter of Randusari (plate C); inscription in Kawi script (see nos. 14439-14453)] OD-14450.
- Kosasih, Dede. 2010. "Kosmologi Sistem Nama Diri (Antroponim) Masyarakat Sunda: dalam Konstelasi Perubahan Struktur Sosial Budaya". Makalah disajikan dalam Seminar Internasional ”Hari Bahasa Ibu” dengan tema: ”Menyelamatkan Bahasa Ibu sebagai Kekayaan Budaya Nasional” di Gedung Merdeka tanggal 19-20 Februari 2010
- MacDonnel, Arthur A. 1893. "Sanskrit-English Dictionary". New York: Longmans Green and Co
- Magli, Giulio. 2009. "Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy From Giza to Easter Island". New York:Copercinus Books
- Mahsun. 2010. "Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik Dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Meskell, Lynn and Preucel, Robert W.(Ed). 2007. "A Companion to Social Archaeology". New Jersey: Blackwell Publishing Ltd.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. "Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir". Jakarta: Komunitas Bambu
- Schimmel, Annemarie. 1989. "Islamic Names". Edinburg :Edinburg University Press.
- Sedyawati, Edi. 1986. “Kajian Kuantitatif Atas Masalah Local Genius ”, dalam Pertemuan Ilmiah ArkeologiIV 3-9 Maret, CipanasStets, Jan E. And Serpe Richard T. , 2016, New Directions in Identity Theory and Research, New York : Oxford University Press
- Stutterheim, W. F. 1940. “Oorkonde van Balitung Uit 905 A.D (Randoesari I)”, dalam INI1, 1940, hal. 4 –7.
- Tjahjono, Baskoro Daru dan Rangkuti, Nurhadi. 1998. “Penetapan Sīma Dalam Konteks Perluasan Wilayah Pada Masa Klasik: Kajian Berdasar Prasasti-Prasasti Balitung (899-910 M)”, dalam Berkala Arkeologi, th XVIII, Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Widodo, Sahid Teguh. 2001. “Nama Diri Masyarakat Jawa”. Disertasi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Zabeeh, Farahang. 1968. "What Is In A Name: An Inquiry into The Semantics and Pragmatics of Proper Name". The Hague: Martinus Nijhoff